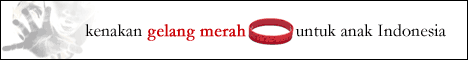Pulau Komodo secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang memiliki habitat asli hewan komodo yang dikelola oleh Pemerintah Pusat karena telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Komodo. UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia pada 1986. Letak Pulau Komodo berada diperbatasan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh Selat Sape.
Bukan cuma di Pulau Komodo binatang komodo berkembang biak dengan baik. Beberapa pulau dikenal memiliki habitat komodo seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Pada kedua pulau tersebut terdapat sekitar 2.500 ekor komodo hingga Agustus 2009, lebih banyak ketimbang populasi komodo di Pulau Komodo yang hanya sekitar 1.300 ekor. Di daratan Pulau Flores yang tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo juga terdapat sekitar 100 ekor komodo di Cagar Alam Wae Wuul.
Perjalanan Pulau Komodo sebagai nominasi dimulai pada Desember 2007 ketika terpilih tiga destinasi wisata Indonesia: Taman Nasional Komodo, Danau Toba, dan Anak Gunung Krakatau dinominasikan bersama dengan 440 nominasi dari 220 Negara. Pemerintah Indonesia mendaftar sebagai OSC dan membayar biaya administrasi masing-masing destinasi USD 199 pada Agustus 2008. Penetapan Taman Nasional Komodo menjadi Indonesia National Nominees bersama 28 finalis lainnya pada tanggal 21 Juli 2009.
Kredibilitas Penyelenggara
Menjelang penentuan pemenang tujuh keajaiban dunia (New 7 Wonders of Nature) pada tanggal 11 November 2011 mendatang, isu Pulau Komodo sebagai salah satu finalis menjadi semakin hangat. Sepuluh hari menjelang pengumuman finalis tujuh keajaiban, Pulau Komodo dari Indonesia menempati urutan ke lima dari 28 finalis setelah Hutan Amazon di Amerika Serikat, Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Sungai Puerto Princize di Filipina. Posisi Komodo ditempel ketat Pulau Bu Tinah dari Uni Emirat Arab di posisi keenam dan Angel Falls dari Bolivia di posisi ketujuh, hingga Selasa (1/11/2011). Ditengarai dibalik kontes yang diadakan oleh New 7 Wonders Foundation ada unsur penipuan. Selain itu, juga ada agenda bisnis terselubung yang membonceng yakni agen promosi yang membisniskan melalui SMS.
Pada kategori unsur penipuan, New 7 Wonders Foundation yang berpusat di Swiss sebagai penyelenggara kontes memintai $200 untuk pendaftaran pada ratusan negara yang ingin menjadi peserta. Awalnya ada 440 lokasi dari 220 negara, lalu disaring menjadi 77 nominasi, lalu disaring lagi menjadi 28 finalis dan selanjutnya diserahkan ke masyarakat untuk memberi dukungan menjadi Tujuh Keajaiban Dunia. Setelah nominasi tinggal 28, kembali pihak New 7 Wonders Foundation mengajukan biaya license fee sebesar 10 juta dolar AS dengan alasan untuk membiayai pesta pengumuman juara.
Penawaran kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah deklarasi N7W diajukan pihak New 7 Wonder Foundation pada Februari 2010. Pemerintah Indonesia menyatakan berminat menjadi tuan rumah pada 25 November 2010. Kemudian pada 6 Desember 2010, pihak N7W menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah dengan license fee sebesar 10 juta dolar AS. Indonesia diberi batas waktu sampai 31 Januari 2011 untuk menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah. Apabila Indonesia tidak menyatakan bersedia, status Taman Nasional Komodo sebagai finalis N7W ditangguhkan, sebagaimana ancaman Kepala Komunikasi N7W Eamon Fitzgerald pada 29 Desember 2010.
Kemudian Kementerian Pariwisata mengutus satu delegasi beranggotakan delapan orang yang terdiri dari pejabat kementerian, seorang pengacara dari Kantor Pengacara “Lubis, Santosa & Maulana”, dan beberapa wartawan nasional untuk menyelidiki keberadaan N7W 28 April 2011. Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, membantu delegasi dari Jakarta untuk penyelidikan itu dan mengadakan kunjungan ke alamat yang tertulis sebagai kantor Yayasan N7W: Hoschgasse 8, PO Box 1212, 8034 Zurich. Ternyata alamat tersebut tidak sesuai karena seharusnya Hoschgasse 8, PO Box 1212, 8008 Zurich. Alamat tersebut adalah Museum Heidi Weber yang diarsiteki Le Corbusier dan selesai dibangun pada 1967 dan hanya terbuka pada musim panas (Juni, Juli, Agustus) dari jam 14.00-17.00.
Selain New 7 Wonders Foundation tidak memiliki lokasi fisik maupun alamat pos juga tidak memiliki afiliasi dengan UNESCO. Pada situs New7Wonders sebelumnya juga pernah mencantumkan logo UNESCO, kemudian UNESCO mengklarifikasi bahwa New7Wonders bukan menjadi bagiannya. UNESCO pun tidak mendukung acara kontes tersebut. UNESCO sampai mengeluarkan pernyataan tersendiri yang menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan dengan penetapan Situs-Situs Warisan Dunia sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh New7Wonders. Hal ini menimbulkan tanda tanya kredibilitas penyelenggara kontes sehingga beberapa negara sempat mengancam mundur, termasuk Indonesia. Sementara pemerintah Maladewa (Maldives), salah satu dari 28 finalis sudah resmi mundur.
Kesaksian Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo juga meragukan kredibilitas Yayasan New7Wonders sebagai penyelenggara pemilihan tujuh keajaiban dunia. KBRI Swiss yang melakukan penyelidikan menemukan bahwa alamat Yayasan New7Wonders tidak jelas, status badan hukumnya juga tidak jelas, serta di mata masyarakat Swiss tidak dikenal. Yayasan New7Wonders hanya memiliki alamat e-mail, berbadan hukum Swiss, berdiri di Panama, sedang pengacaranya berada di Inggris.
Pihak agen promosipun (Content Provider Indonesia) memanfaatkan untuk tujuan bisnis kerjasama dengan Pendukung Pemenangan Komodo. Pendukung ini kemudian menjalin kerjasama dengan empat provider telekomunikasi untuk melancarkan dukungan SMS. Awalnya biaya untuk mengirimkan pesan singkat telepon genggam (SMS) Komodo ke 9818 sebesar Rp 1.000. Ketika tarif SMS masih Rp 1.000, tidak jelas keberadaan dana itu, apakah benar disalurkan untuk P. Komodo ataupun turisme Indonesia? Setelah banyak dipertanyakan, operator dan CP menurunkan tarif menjadi Rp 1. Telkomsel secara khusus mengirim Value Added Service (VAS) SMS ke pelanggannya di Indonesia baik Kartu Halo, SimPATI, dan AS dengan pesan "Dukung Komodo Jadi Bagian 7 Keajaiban Dunia. Ketik KOMODO kirim ke 9818, tarif Rp1.
Kini ketika tarif menjadi Rp 1 dan sudah banyak dukungan dari publik figur termasuk Jusuf Kalla, termasuk Presiden SBY, masyarakat Indonesia semakin antusias mengirimkan SMS dukungan. Dukungan artis seperti Olga Lydia, Fadli Padi, grup band Slank, RAN dan lainnya turut mengatrol dukungan SMS. Tercatat ketika group band Slank mengumumkan dukungannya, jumlah SMS yang masuk 10 juta dalam sehari. Hingga H-12 hari penentuan, jumlah SMS telah menembus 100 juta lebih yang dikirim masyarakat ke nomor 9818. Penyedia layanan SMS Mobilink pun sampai menaikkan kapasitas servernya. Namun tidak jelas besarnya pembagian keuntungan antara pihak CP, operator, dan pemerintah dan pihak lainnya yang mengurusi pariwisata Pulau Komodo.
Besarnya dukungan masyarakat Indonesia di dalam maupun di luar negeri melalui televoting SMS karena akan diiming-imingi oleh Panitia Lokal Indonesia. Warga negara Indonesia diluar negeripun bisa mengirimkan SMS dukungan terhadap Komodo dengan nomor tujuan sesuai operator telekomunikasi setempat. Para TKI yang berada di Korea pun antusias berpartisipasi mendukung Komodo, sekalipun Korea juga masuk menjadi finalis mengunggulkan Pulau Jeju. Bagi yang telah mengirim 100 kali SMS akan diabadikan namanya di Monumen Komodo sebagai saksi sejarah, dalam ajang finalis tujuh keajaiban dunia pada 2011. Yayasan Pendiri 7 Keajaiban Dunia (New 7 Wonder Foundation) menargetkan bisa meraih sebanyak 1 miliar SMS. Dalam kaitan dengan pemenangan Komodo, di Indonesia dibentuk Pendukung Pemenangan Komodo (P2 Komodo) sebagai lembaga di Indonesia yang mendapat lisensi untuk mengelola dukungan terkait penjurian 7 Keajaiban Dunia.
Hiruk pikuk pemenangan Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia, posisi pemerintah tetap pada pendirian yakni tidak ikut proses koordinasi voting untuk Pulau Komodo. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memandang vote Komodo itu inisiatif dari sekelompok orang di luar pemerintah karena yayasan New 7 Wonder tidak cukup kredibel. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Presiden SBY ikut menyerukan televoting SMS pemenangan Pulau Komodo sementara posisi Kementerian Pariwisata telah menyatakan tidak ikut dalam koordinasi voting itu?
Kita tahu, Presiden SBY pada peresmian Bandara Internasional Lombok Kamis (20/10/2011) diatas podium mengajak masyarakat mendukung Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam kesempatan itu termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Mantan Wapres Jusuf Kalla yang menjadi Duta Komodo hadir dengan menggunakan pakaian batik.
Kini isu pemenangan Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia berubah menjadi ibarat komedi yang lucu tapi tidak menggelikan. Akan lebih baik bila dana pemenangan Komodo digunakan untuk konservasi Komodo yang semakin langka ketimbang digunakan untuk biaya kampanye pemenangan yang tidak jelas kriteria penjuriannya dan kredibilitas lembaga penyelenggaranya pun dipertanyakan. (Muslimin B. Putra, Penulis, Peminat Isu Kebijakan Publik, Cepsis Makassar)
Tampilkan postingan dengan label CEPSIS Makassar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CEPSIS Makassar. Tampilkan semua postingan
11/13/2011
10/26/2011
Reformasi Birokrasi Setengah Hati
Pada tahun kedua kepemimpinan SBY-Boediono, terjadi reshuffle kabinet dengan merombak beberapa menteri dan menambah posisi wakil menteri pada beberapa kementerian. Dari sebelumnya tujuh wakil menteri menjadi 20 wakil menteri. Aturan khusus pun dibuat untuk melegitimasi keberadaan Wakil Menteri yang tidak harus pejabat eselon I-A untuk mengakomodir calon Wakil Menteri tertentu. Aturan khusus yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tertanggal 13 Oktober 2011.
Dengan terbitnya Perpres No 76/2011, maka terlegitimasilah beberapa calon Wakil Presiden untuk menduduki posisinya secara legal-konstitusional. Posisi wakil menteri diduduki oleh pegawai negeri sipil dan memiliki jenjang karier disetarakan sebagaimana pejabat eselon I-A. Padahal defenisi pejabat karier sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 70 ayat 3 adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I-A.
Bila Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menyebabkan Anggito Abimanyo terganjal sebagai calon wakil menteri keuangan, maka dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 memuluskan jalan bagi Denny Indrayana sebagai calon Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal keduanya, pada saat pengangkatannya dalam waktu yang berbeda masih belum tercatat sebagai pejabat eselon I-A. Disinilah letak watak rezim SBY-Boediono yang berwatak kekuasaan belaka, bukan berwatak pada konstitusi.
Dengan hadirnya 19 posisi Wakil Menteri pada 17 kementerian merupakan sejarah baru dalam struktur administrasi negara di Indonesia. Konsekuensinya, adalah tugas dan fungsi antara menteri dan wakil menteri harus jelas pengaturan dan prosedur kerjanya. Selain itu, bertambahnya struktur wakil menteri membuat anggaran belanja negara membengkak karena harus menyediakan fasilitas dinas dan anggaran rutin bagi posisi wakil-wakil menteri yang baru.
Ada argumentasi dari rezim SBY bahwa penambahan wakil menteri adalah langkah strategis Presiden untuk meningkatkan kinerja kementerian. Penempatan pejabat karir sebagai wakil menteri juga sebagai upaya peningkatam kualitas proses perumusan kebijakan untuk menghasilkan sinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada masing-masing kementrian. Namun faktanya, wakil menteri yang sudah dua tahun terbentuk pada jajaran kementerian perekonomian nyaris tidak terpakai dan tidak berdampak pada peningkatan kinerja kementeriannya. Bahkan terkesan, keberadaan wakil menteri tersebut dapat memperpanjang alur birokrasi dan mempersulit dunia usaha.
Dalam hal pengangkatan pos wakil menteri, rezim SBY berlindung dibalik UU No. 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU tersebut mengijinkan seorang Presiden untuk mengangkat wakil menteri di departemen yang dianggap perlu yang dijabat oleh pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet, berbeda dengan menterinya meski memiliki beban tugas yang sama atau lebih.
Bertambahnya struktur baru dalam kelembagaan negara berpotensi memperpanjang rentang kendali antar sub-struktur dalam organisasi kementerian. Koordinasi antar lini dalam manajemen organisasi kementerian yang baru dapat menjadi masalah latent. Apalagi Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet yang akan mempersulit nantinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis di kementerian yang dipimpinnya sehingga terkesan struktur baru Wakil Menteri hanya asesoris politik belaka.
Setiap struktur baru dalam organisasi kementerian akan membuat alur birokrasi yang lebih panjang. Prinsip efektif dan efisien akan jauh untuk tercapai apabila desain struktur birokrasi menjadi panjang dan justru akan menghasilkan masalah-masalah baru dalam birokrasi yang disebut berau-pathology. Bila tidak ada rule of conduct berdasarkan undang-undang kementerian negara, posisi menteri dan wakil menteri kesulitan membagi tugasnya serta dapat membangkitkan persaingan antara menteri dan wakil menteri karena persoalan orientasi dan tujuan yang berbeda.
Semestinya seorang menteri yang sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalamannya tidak memerlukan posisi wakil menteri. Apalagi, dalam kelembagaan kementerian terdapat para pejabat karier setingkat eselon I pada level dirjen dan sekjen yang telah menguasai masalah didalam kementeriannya. Selama ini didalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dilantik pada 20 Oktober 2009, posisi wakil menteri hanya berada pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam rentang waktu 2009-2010, Presiden SBY kemudian melantik 10 wakil menteri. Pada tahun 2011, kembali menambah pos wakil menteri pada tujuh kementerian seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, Luar Negeri, Kebudayaan dan Pariwisata, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Agama. Namun belum ada evaluasi dan audit kinerja posisi wakil menteri pada kelima kementerian tersebut, kini pasca reshuffle justru membengkak posisi menjadi 19 pos wakil menteri.
Contoh kinerja yang tidak sejalan antara menteri dan wakil menteri adalah di kementerian pertanian. Pernyataan wakil menteri pertanian kerapkali dikoreksi oleh menteri yang bersangkutan dan kerap terjadi benturan kepentingan. Lemahnya posisi wakil menteri yang bukan anggota kabinet menjadi masalah tersendiri, sementara menteri merupakan anggota kabinet yang memiliki kepentingan politik. Selama dua tahun berjalan, belum ada tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) antara menteri dan wakil menteri pada kelima kementerian sebagaimana disebut diatas.
Adanya struktur baru pada banyak kementerian berimplikasi pada pemborosan keuangan negara. Mengapa demikian? Karena anggaran negara didalam APBN mengikuti struktur pemerintahan, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi, meski tidak dibutuhkan tapi karena kehadiran struktur baru menyebabkan negara harus mengalokasikan anggaran negara agar menjaga kelangsungan hidup organisasi kementerian.
Dengan membengkaknya birokrasi didalam struktur organisasi kementerian bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Pembengkakan birokrasi pemerintahan akan memperburuk kinerja organisasi pemerintahan dengan ciri inefisiensi dan pemborosan anggaran negara. Padahal semestinya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memiliki struktur birokrasi yang linear dan ramping. Bahkan seharusnya beberapa pejabat eselon I yang tak diperlukan dihilangkan atau dilebur saja agar alur birokrasi lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Bertambahnya struktur baru didalam organisasi kementerian bukanlah pekerjaan mudah karena akan berpengaruh pada budaya organisasi. Budaya organisasi di kementerian selama ini terbiasa dengan struktur organisasi yang menempatkan menteri sebagai orang nomor satu. Sedangkan posisi nomor dua adalah sekretaris jenderal (sekjen), kemudian di bawahnya terdapat para direktur jenderal (dirjen). Kehadiran wakil menteri sebagai orang nomor dua menggeser posisi sekretaris jenderal akan mendatangkan konsekwensi baru berupa budaya organisasi baru. Sementara mengubah budaya organisasi dengan struktur organisasi yang baru memerlukan waktu yang tergolong lama. Apalagi bila tidak ada uraian tugas antara menteri dan wakil menteri serta pejabat eselon 1 lainnya pada kementerian yang sama.
Bila selama ini, kewenangan, tugas dan fungsi antara sekjen dan dirjen bertanggung jawab langsung ke menteri, maka kehadiran wakil menteri akan berpengaruh dan mengubah kebiasaan tersebut. Bila tidak ada ketegasan tugas antara menteri dan wakil menteri, maka bisa saja terjadi rivalitas pada kedua jabatan tersebut. Terlbih bila wakil menteri tidak berwenang merumuskan dan membuat keputusan atau kebijakan, maka bisa saja sekjen dan para dirjen tidak memedulikan wakil menteri dalam aktifitas administrasi negara di kementeriannya.
Akhirul kalam, penambahan posisi wakil menteri bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan adanya efisiensi kerja. Spirit perampingan pegawai/pejabat negara dan penghematan belanja pegawai/pejabat negara justru digemukkan oleh rezim SBY-Boediono. Slogan reformasi birokrasi hanya lip service dan dijalankan setengah hati oleh seorang presiden SBY.
Dengan terbitnya Perpres No 76/2011, maka terlegitimasilah beberapa calon Wakil Presiden untuk menduduki posisinya secara legal-konstitusional. Posisi wakil menteri diduduki oleh pegawai negeri sipil dan memiliki jenjang karier disetarakan sebagaimana pejabat eselon I-A. Padahal defenisi pejabat karier sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 70 ayat 3 adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I-A.
Bila Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menyebabkan Anggito Abimanyo terganjal sebagai calon wakil menteri keuangan, maka dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 memuluskan jalan bagi Denny Indrayana sebagai calon Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal keduanya, pada saat pengangkatannya dalam waktu yang berbeda masih belum tercatat sebagai pejabat eselon I-A. Disinilah letak watak rezim SBY-Boediono yang berwatak kekuasaan belaka, bukan berwatak pada konstitusi.
Dengan hadirnya 19 posisi Wakil Menteri pada 17 kementerian merupakan sejarah baru dalam struktur administrasi negara di Indonesia. Konsekuensinya, adalah tugas dan fungsi antara menteri dan wakil menteri harus jelas pengaturan dan prosedur kerjanya. Selain itu, bertambahnya struktur wakil menteri membuat anggaran belanja negara membengkak karena harus menyediakan fasilitas dinas dan anggaran rutin bagi posisi wakil-wakil menteri yang baru.
Ada argumentasi dari rezim SBY bahwa penambahan wakil menteri adalah langkah strategis Presiden untuk meningkatkan kinerja kementerian. Penempatan pejabat karir sebagai wakil menteri juga sebagai upaya peningkatam kualitas proses perumusan kebijakan untuk menghasilkan sinergi dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada masing-masing kementrian. Namun faktanya, wakil menteri yang sudah dua tahun terbentuk pada jajaran kementerian perekonomian nyaris tidak terpakai dan tidak berdampak pada peningkatan kinerja kementeriannya. Bahkan terkesan, keberadaan wakil menteri tersebut dapat memperpanjang alur birokrasi dan mempersulit dunia usaha.
Dalam hal pengangkatan pos wakil menteri, rezim SBY berlindung dibalik UU No. 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU tersebut mengijinkan seorang Presiden untuk mengangkat wakil menteri di departemen yang dianggap perlu yang dijabat oleh pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan anggota kabinet, berbeda dengan menterinya meski memiliki beban tugas yang sama atau lebih.
Bertambahnya struktur baru dalam kelembagaan negara berpotensi memperpanjang rentang kendali antar sub-struktur dalam organisasi kementerian. Koordinasi antar lini dalam manajemen organisasi kementerian yang baru dapat menjadi masalah latent. Apalagi Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet yang akan mempersulit nantinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis di kementerian yang dipimpinnya sehingga terkesan struktur baru Wakil Menteri hanya asesoris politik belaka.
Setiap struktur baru dalam organisasi kementerian akan membuat alur birokrasi yang lebih panjang. Prinsip efektif dan efisien akan jauh untuk tercapai apabila desain struktur birokrasi menjadi panjang dan justru akan menghasilkan masalah-masalah baru dalam birokrasi yang disebut berau-pathology. Bila tidak ada rule of conduct berdasarkan undang-undang kementerian negara, posisi menteri dan wakil menteri kesulitan membagi tugasnya serta dapat membangkitkan persaingan antara menteri dan wakil menteri karena persoalan orientasi dan tujuan yang berbeda.
Semestinya seorang menteri yang sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalamannya tidak memerlukan posisi wakil menteri. Apalagi, dalam kelembagaan kementerian terdapat para pejabat karier setingkat eselon I pada level dirjen dan sekjen yang telah menguasai masalah didalam kementeriannya. Selama ini didalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dilantik pada 20 Oktober 2009, posisi wakil menteri hanya berada pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam rentang waktu 2009-2010, Presiden SBY kemudian melantik 10 wakil menteri. Pada tahun 2011, kembali menambah pos wakil menteri pada tujuh kementerian seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, Luar Negeri, Kebudayaan dan Pariwisata, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Agama. Namun belum ada evaluasi dan audit kinerja posisi wakil menteri pada kelima kementerian tersebut, kini pasca reshuffle justru membengkak posisi menjadi 19 pos wakil menteri.
Contoh kinerja yang tidak sejalan antara menteri dan wakil menteri adalah di kementerian pertanian. Pernyataan wakil menteri pertanian kerapkali dikoreksi oleh menteri yang bersangkutan dan kerap terjadi benturan kepentingan. Lemahnya posisi wakil menteri yang bukan anggota kabinet menjadi masalah tersendiri, sementara menteri merupakan anggota kabinet yang memiliki kepentingan politik. Selama dua tahun berjalan, belum ada tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) antara menteri dan wakil menteri pada kelima kementerian sebagaimana disebut diatas.
Adanya struktur baru pada banyak kementerian berimplikasi pada pemborosan keuangan negara. Mengapa demikian? Karena anggaran negara didalam APBN mengikuti struktur pemerintahan, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi, meski tidak dibutuhkan tapi karena kehadiran struktur baru menyebabkan negara harus mengalokasikan anggaran negara agar menjaga kelangsungan hidup organisasi kementerian.
Dengan membengkaknya birokrasi didalam struktur organisasi kementerian bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Pembengkakan birokrasi pemerintahan akan memperburuk kinerja organisasi pemerintahan dengan ciri inefisiensi dan pemborosan anggaran negara. Padahal semestinya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memiliki struktur birokrasi yang linear dan ramping. Bahkan seharusnya beberapa pejabat eselon I yang tak diperlukan dihilangkan atau dilebur saja agar alur birokrasi lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Bertambahnya struktur baru didalam organisasi kementerian bukanlah pekerjaan mudah karena akan berpengaruh pada budaya organisasi. Budaya organisasi di kementerian selama ini terbiasa dengan struktur organisasi yang menempatkan menteri sebagai orang nomor satu. Sedangkan posisi nomor dua adalah sekretaris jenderal (sekjen), kemudian di bawahnya terdapat para direktur jenderal (dirjen). Kehadiran wakil menteri sebagai orang nomor dua menggeser posisi sekretaris jenderal akan mendatangkan konsekwensi baru berupa budaya organisasi baru. Sementara mengubah budaya organisasi dengan struktur organisasi yang baru memerlukan waktu yang tergolong lama. Apalagi bila tidak ada uraian tugas antara menteri dan wakil menteri serta pejabat eselon 1 lainnya pada kementerian yang sama.
Bila selama ini, kewenangan, tugas dan fungsi antara sekjen dan dirjen bertanggung jawab langsung ke menteri, maka kehadiran wakil menteri akan berpengaruh dan mengubah kebiasaan tersebut. Bila tidak ada ketegasan tugas antara menteri dan wakil menteri, maka bisa saja terjadi rivalitas pada kedua jabatan tersebut. Terlbih bila wakil menteri tidak berwenang merumuskan dan membuat keputusan atau kebijakan, maka bisa saja sekjen dan para dirjen tidak memedulikan wakil menteri dalam aktifitas administrasi negara di kementeriannya.
Akhirul kalam, penambahan posisi wakil menteri bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan adanya efisiensi kerja. Spirit perampingan pegawai/pejabat negara dan penghematan belanja pegawai/pejabat negara justru digemukkan oleh rezim SBY-Boediono. Slogan reformasi birokrasi hanya lip service dan dijalankan setengah hati oleh seorang presiden SBY.
1/29/2011
Menimbang Kebijakan Penyewaan Hutan
Satu lagi kebijakan negara disoal oleh masyarakat yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP ini mengatur tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan. Kebijakan ini seakan memberi justifikasi terhadap penyewaan hutan, layaknya rental mobil yang dapat dipersewakan kepada siapa saja. Kebijakan ini kontan mendapatkan respon negatif dari kalangan masyarakat sipil karena kebijakan ini dapat mempersubur praktek illegal logging yang sudah banyak merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan ini dapat mempercepat laju kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia yang mencapai 2,7 juta hektar per tahun. Tanpa diberikan izin pun, laju perusakan hutan termasuk hutan lindung sudah terjadi dan terus berlangsung.
Menurut Presiden SBY usai memimpin rapat di Departemen Kehutanan hari Jumat (22/2) siang, didampingi Wapres Jusuf Kalla dan para menteri mengatakan bahwa, ”PP No 2/2008 sesungguhnya adalah berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang terbit tahun 2004 yang lalu, yakni PP Nomor 1 tahun 2004 sebagai revisi dari UU nomor 41 tahun 1999. PP ini juga adalah tindaklanjut dari Keppres No.41 tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yang mengatur 13 ijin tetap yang diberikan kepada mereka yang berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan. Kemudian diatur lebih lanjut, bagaimana agar mereka memberikan kontribusi untuk negara, dimana kontribusi itu penting untuk memelihara, merehabilitasi dan menghutankan kembali kawasan- kawasan itu. Itulah sesungguhnya yang diatur atau jiwa dan semangat dari PP No 2 tahun 2008 itu," kata Presiden.
Sebagai bawahan presiden, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban memberi penjelasan lebih lanjut bahwa selama ini sebenarnya banyak kawasan hutan yang sudah dipinjam-pakaikan untuk kepentingan selain kehutanan, seperti pemasangan tower, tambang oleh Pertamina atau perusahaan minyak dan lain-lain, dengan aturannya memberikan lahan pengganti. Tetapi sekarang ini lahan pengganti sudah semakin sulit. Jadi sebenarnya ada perubahan yang tadinya menggunakan lahan pengganti, sekarang diminta kompensasi untuk digunakan Dephut memperluas kawasan-kawasan hutan, membeli atau merehabilitasi kawasan-kawasan yang ada. "Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan penyewaan, karena pemerintah tidak menyewakan. Pemerintah minta kompensasi. Dan perlu diingat, semua perusahaan ini kewajibannya bukan hanya semata mata tarif dari pemanfaatan kawasannya, tetapi juga ada kewajiban membayar DRPSDH atau Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan, serta membayar kewajiban PBB atau pajak-pajak lainnya," jelas MS Ka`ban. Dari penerbitan PP ini, pihak Departemen Kehutanan sendiri menargetkan PNBP sebesar Rp 600 miliar. Angka ini tidak sebanding dengan potensi kerugian yang akan membebani APBN bila bencana alam terjadi akibat kerusakan hutan. Malah prediksi Greenomics Indonesia menyatakan kerugian ekologi-ekonomi akibat PP ini bisa mencapai tidak kurang dari Rp 70 triliun per tahun.
Dari dua statemen pemerintah pemegang otoritas kehutanan, tersirat adanya pengalihan semangat melanjutkan memori publik bahwa kebijakan tersebut adalah kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Padahal sejatinya, kebijakan ini adalah legitmiasi terhadap kebijakan penyewaan hutan untuk tujuan penerimaan keuangan negara dan kontraproduktif dengan semangat mengurangi emisi gas rumah kaca dalam konteks global warming dan perubahan iklim.
Pertentangan Kebijakan
Penerbitan PP No. 2/2008 dapat dikategorikan bertentangan dengan kebijakan lebih tinggi yakni Undang-Undang (UU). PP No. 2/2008 yang memberi izin dilakukannya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) UU No. 41/1999 tentang penggunaan kawasan hutan. Ayat ini menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pada ayat (4) juga disebutkan bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola tambang terbuka.
Pertentangan lainnya adalah persoalan fungsi pokok kawasan hutan lindung. PP No. 2/2008 dapat mengakibatkan berubahnya fungsi pokok kawasan hutan, sementara Pasal 1 Angka (8) UU No. 41/1999 menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga tersebut meliputi pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Bla terjadi perubahan fungsi pokok kawasan hutan karena tekanan modal (baca: uang) sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2008, maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat berupa ancaman bencana alam seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau disamping secara makro hancurnya infrastruktur, hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam.
Selain masalah konten PP yang bertentangan dengan UU, PP No. 2/2008 juga secara hirarki peraturan perundang-udangan menyalahi pakem yang umum digunakan di Indonesia. Pada dasarnya keberadaan PP untuk menjelaskan sebuah UU yagn berada pada tingkat lebih tinggi. Namun ironisnya, PP No. 02/2008 tidak bermaksud untuk itu karena tidak menjelaskan UU mana yang dijelaskan, melainkan hanya menjelaskan aturan penyewaan hutan berdasarkan logika ekonomi. Malah ironisnya, PP No. 02/2008 justru menjelaskan aturan yang sama tingkatannya yaitu PP No. 22/1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kemudian diubah menjadi PP No. 52/1998 atau dengan kata lain PP menjelaskan PP.
Semestinya rezim SBY-JK dapat mencontoh politik hukum ala rezim BJ Habibie yang menelorkan UU No. 41/1999 yang banyak mengilhami pemimpin negara-negara di dunia untuk melarang pertambangan terbuka di hutan lindung seperti Abel Apcheo, Presiden Kostarika, Presiden Ekuador dan pemerintah Kanada dan Argentina. Pada masa itu, Menteri Kehutanan dijabat oleh Dr. Muslimin Nasution, seorang teknokrat berlatar belakang ICMI.
Maka tak salah bila Ketua YLBHI, Patra M Zen menganggap bahwa klaim presiden SBY - sebagaimana dikutip dimuka - untuk menyelamatkan hutan melalui PP No. 02/2008 karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak menjadi dasar pertimbangan dari PP ini.
Penerbitan PP ini, semakin memperjelas watak rezim SBY-JK yang lebih mengedepankan idiologi politik ekonomi kapitalis karena lebih mementingkan kebijakan yang dapat memberi imbalan uang ketimbang keberlanjutan ekologi-ekonomi masyarakat banyak. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan resiko penyewaan hutan yang berpotensi membawa kesengsaraan masyarakat akibat ancaman bencana alam. Sepertinya rezim ini tidak berkaca pada pengalaman beberapa waktu lalu ketika merebak serangkaian bencana alam baik secara langsung maupun tidak langsung akibat kerusakan hutan.
Bila PP ini tidak dicabut, maka tak salah bila publik bisa mencap rezim SBY sebagai rezim agent kapitalis yang tidak berpihak pada kepentingan publik melainkan hanya kepada para kapitalis (pemilik modal). Kebijakan penyewaan hutan tidak beda dengan rental mobil, dimana pihak penyewa tidak memiliki kewajiban menjaga keberlangsungan obyek yang disewanya karena merasa telah memberi imbalan uang sewa.
Bila watak ekonomi-politik pro kapitalis, maka alamat bagi bencana alam akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang diakibatkan oleh penggundulan hutan akan menjadi dampak langsung dari PP ini. Sedang dampak tak langsung adalah terjadinya proses pemiskinan secara terus menerus dari akibat bencana alam yang mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Menurut Presiden SBY usai memimpin rapat di Departemen Kehutanan hari Jumat (22/2) siang, didampingi Wapres Jusuf Kalla dan para menteri mengatakan bahwa, ”PP No 2/2008 sesungguhnya adalah berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang terbit tahun 2004 yang lalu, yakni PP Nomor 1 tahun 2004 sebagai revisi dari UU nomor 41 tahun 1999. PP ini juga adalah tindaklanjut dari Keppres No.41 tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yang mengatur 13 ijin tetap yang diberikan kepada mereka yang berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan. Kemudian diatur lebih lanjut, bagaimana agar mereka memberikan kontribusi untuk negara, dimana kontribusi itu penting untuk memelihara, merehabilitasi dan menghutankan kembali kawasan- kawasan itu. Itulah sesungguhnya yang diatur atau jiwa dan semangat dari PP No 2 tahun 2008 itu," kata Presiden.
Sebagai bawahan presiden, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban memberi penjelasan lebih lanjut bahwa selama ini sebenarnya banyak kawasan hutan yang sudah dipinjam-pakaikan untuk kepentingan selain kehutanan, seperti pemasangan tower, tambang oleh Pertamina atau perusahaan minyak dan lain-lain, dengan aturannya memberikan lahan pengganti. Tetapi sekarang ini lahan pengganti sudah semakin sulit. Jadi sebenarnya ada perubahan yang tadinya menggunakan lahan pengganti, sekarang diminta kompensasi untuk digunakan Dephut memperluas kawasan-kawasan hutan, membeli atau merehabilitasi kawasan-kawasan yang ada. "Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan penyewaan, karena pemerintah tidak menyewakan. Pemerintah minta kompensasi. Dan perlu diingat, semua perusahaan ini kewajibannya bukan hanya semata mata tarif dari pemanfaatan kawasannya, tetapi juga ada kewajiban membayar DRPSDH atau Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan, serta membayar kewajiban PBB atau pajak-pajak lainnya," jelas MS Ka`ban. Dari penerbitan PP ini, pihak Departemen Kehutanan sendiri menargetkan PNBP sebesar Rp 600 miliar. Angka ini tidak sebanding dengan potensi kerugian yang akan membebani APBN bila bencana alam terjadi akibat kerusakan hutan. Malah prediksi Greenomics Indonesia menyatakan kerugian ekologi-ekonomi akibat PP ini bisa mencapai tidak kurang dari Rp 70 triliun per tahun.
Dari dua statemen pemerintah pemegang otoritas kehutanan, tersirat adanya pengalihan semangat melanjutkan memori publik bahwa kebijakan tersebut adalah kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Padahal sejatinya, kebijakan ini adalah legitmiasi terhadap kebijakan penyewaan hutan untuk tujuan penerimaan keuangan negara dan kontraproduktif dengan semangat mengurangi emisi gas rumah kaca dalam konteks global warming dan perubahan iklim.
Pertentangan Kebijakan
Penerbitan PP No. 2/2008 dapat dikategorikan bertentangan dengan kebijakan lebih tinggi yakni Undang-Undang (UU). PP No. 2/2008 yang memberi izin dilakukannya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) UU No. 41/1999 tentang penggunaan kawasan hutan. Ayat ini menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pada ayat (4) juga disebutkan bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola tambang terbuka.
Pertentangan lainnya adalah persoalan fungsi pokok kawasan hutan lindung. PP No. 2/2008 dapat mengakibatkan berubahnya fungsi pokok kawasan hutan, sementara Pasal 1 Angka (8) UU No. 41/1999 menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga tersebut meliputi pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Bla terjadi perubahan fungsi pokok kawasan hutan karena tekanan modal (baca: uang) sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2008, maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat berupa ancaman bencana alam seperti banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau disamping secara makro hancurnya infrastruktur, hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity) yang menjadi bagian sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam.
Selain masalah konten PP yang bertentangan dengan UU, PP No. 2/2008 juga secara hirarki peraturan perundang-udangan menyalahi pakem yang umum digunakan di Indonesia. Pada dasarnya keberadaan PP untuk menjelaskan sebuah UU yagn berada pada tingkat lebih tinggi. Namun ironisnya, PP No. 02/2008 tidak bermaksud untuk itu karena tidak menjelaskan UU mana yang dijelaskan, melainkan hanya menjelaskan aturan penyewaan hutan berdasarkan logika ekonomi. Malah ironisnya, PP No. 02/2008 justru menjelaskan aturan yang sama tingkatannya yaitu PP No. 22/1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kemudian diubah menjadi PP No. 52/1998 atau dengan kata lain PP menjelaskan PP.
Semestinya rezim SBY-JK dapat mencontoh politik hukum ala rezim BJ Habibie yang menelorkan UU No. 41/1999 yang banyak mengilhami pemimpin negara-negara di dunia untuk melarang pertambangan terbuka di hutan lindung seperti Abel Apcheo, Presiden Kostarika, Presiden Ekuador dan pemerintah Kanada dan Argentina. Pada masa itu, Menteri Kehutanan dijabat oleh Dr. Muslimin Nasution, seorang teknokrat berlatar belakang ICMI.
Maka tak salah bila Ketua YLBHI, Patra M Zen menganggap bahwa klaim presiden SBY - sebagaimana dikutip dimuka - untuk menyelamatkan hutan melalui PP No. 02/2008 karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak menjadi dasar pertimbangan dari PP ini.
Penerbitan PP ini, semakin memperjelas watak rezim SBY-JK yang lebih mengedepankan idiologi politik ekonomi kapitalis karena lebih mementingkan kebijakan yang dapat memberi imbalan uang ketimbang keberlanjutan ekologi-ekonomi masyarakat banyak. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan resiko penyewaan hutan yang berpotensi membawa kesengsaraan masyarakat akibat ancaman bencana alam. Sepertinya rezim ini tidak berkaca pada pengalaman beberapa waktu lalu ketika merebak serangkaian bencana alam baik secara langsung maupun tidak langsung akibat kerusakan hutan.
Bila PP ini tidak dicabut, maka tak salah bila publik bisa mencap rezim SBY sebagai rezim agent kapitalis yang tidak berpihak pada kepentingan publik melainkan hanya kepada para kapitalis (pemilik modal). Kebijakan penyewaan hutan tidak beda dengan rental mobil, dimana pihak penyewa tidak memiliki kewajiban menjaga keberlangsungan obyek yang disewanya karena merasa telah memberi imbalan uang sewa.
Bila watak ekonomi-politik pro kapitalis, maka alamat bagi bencana alam akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya yang diakibatkan oleh penggundulan hutan akan menjadi dampak langsung dari PP ini. Sedang dampak tak langsung adalah terjadinya proses pemiskinan secara terus menerus dari akibat bencana alam yang mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat.
12/16/2010
Gowa Discovery Park versus UU Cagar Budaya
Masyarakat Sulawesi Selatan akan terancam kehilangan satu situs sejarah Kerajaan Gowa di kawasan Banteng Somba Opu Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar. Sebuah proyek pembangunan kawasan bermain bernama Gowa Discovery Park senilai Rp 20 miliar akan dibangun disekitar kawasan bersejarah tersebut. Proyek Gowa Discovery Park rencananya seluas 17 hektare akan dibangun oleh pengemban PT Mirah Megah Wisata dengan investor PT Makassar Discovery Club milik Zainal Tayeb, seorang pengusaha Bali yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Kelak wahana tersebut berisi: Waterboom, Taman Burung, Taman Gajah, taman olahraga dan bermain, sarana outbond, serta tree top (wahana melintas pohon). Perincian luas wahana taman burung seluas 2 hektare, taman gajah 3 hektare, tree top 2 hektare, dan water boom 3 hektare. Sarana penunjang seperti parkir seluas 2 hektare dengan asumsi jumlah pengunjung pada saat hari raya tetap dapat ditampung serta pembangunan hotel kelas I. Pada wahana taman burung, aneka burung dari berbagai daerah dapat dilihat pengunjung. Wahana tree top disiapkan bagi pengunjung yang hendak menguji nyali, sementara pengunjung yang gemar bermain air disiapkan wahana Water Boom. Proyek pembangunan empat wahana bermain utama rencananya akan rampung dan beroperasi pada Juni 2011.
Dalam desain awal, kawasan Benteng Somba Opu berada di tengah area Gowa Discovery Park. Di dalam area tersebut terdapat sejumlah rumah adat sejumlah kabupaten, seperti rumah adat Toraja dan Bugis. Ada sembilan rumah adat, tidak ada yang kami hilangkan, bahkan kami turut menjaga pemeliharaannya. Investor diharapkan bisa membantu mempublikasikan situs benteng Somba Opu dengan adanya wahana bermain Gowa Discovery agar kawasan Benteng Somba Opu lebih menarik pengunjung. Investor juga menjamin proyek Gowa Discovery tidak akan merusak bangunan cagar budaya yang di dalamnya terdapat rumah adat dari berbagai etnik di Sulawesi Selatan dan Barat itu (tempointeraktif.com). Namun pengamatan beberapa arkeolog menunjukkan adanya kegiatan proyek pada sisi timur ke selatan kawasan benteng yang akan digunakan untuk pembuatan pagar batas kawasan taman burung: mulai dari Baruga Somba Opu sampai ke rumah adat Mamasa.
Proyek Gowa Discovery Park akan dibangun selama satu tahun ke depan. Peletakan batu pertama oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada tanggal 18 Oktober 2010 lalu. Pengelolaan Gowa Discovery Park nantinya dengan sistem bagi hasil selama 30 tahun antara investor 90 persen dengan Pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 10 persen. Saat ini proyek pembangunan masih dalam tahap penimbunan di area seluas 10 hektare. Namun pembangunan proyek dinilai melenceng dari rencana awal yang tidak menyentuh cagar budaya. Sebagian batu bata asal abad ke-17 yang dikumpulkan di dekat tembok benteng dijadikan timbunan bangunan baru. Hal inilah yang memantik pada akademisi dan pihak Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Makassar melakukan penolakan dan dihentikan sementara atas rencana pembangunan proyek.
Situs Benteng
Situs Benteng Somba Opu sebelumnya pernah tertimbun selama kurang lebih 300 tahun setelah dihancurkan oleh penjajah Belanda tahun 1669. Pada tahun 1984, situs Benteng Somba Opu berhasil ditemukan kembali dalam eskapasi yang dipimpin oleh Dr.Muchlis Paeni, sejarawan dari UNHAS. Dalam kegiatan awal eskavasi situs Benteng Somba Opu, pihak Japan Fundation ikut memberikan bantuan dana pada masa pemerintahan Gubernur Sulsel, Prof.Dr.H.Ahmad Amiruddin.
Banteng Somba Opu mulai dibangun pada abad XV oleh Raja Gowa ke-9, Karaeng Tumapparrisi Kallonna kemudian dilanjutkan oleh Raja Gowa ke-10, Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Kawasan Benteng Somba Opu ini pada masa-masa kemahsyurannya merupakan salah satu “Kota Dunia” dengan dilengkapi Pelabuhan Internasional yang paling ramai didatangi pedagang-pedagang dari Eropa di Asia Tenggara. Kebesaran Kerajaan Gowa dengan kota kerajaan Benteng Somba Opu merupakan fakta sejarah yang tidak boleh dihapus oleh pembangunan sarana bermain didalam kota modern.
Bentuk benteng Somba Opu secara utuh berbentuk persegi empat berdasarkan peta hasil stilasi yang dibuat oleh Francois Valentijn dan disempurnakan oleh Bleau pada tahun 1638. Di dalam kawasan banteng Somba Opu terdiri dari istana raja, rumah para bangsawan, pembesar dan para pegawai kerajaan. Di luar tembok benteng yang terbuat dari batu padas dan tanah isian dengan ketebalan bervariasi antara 200 – 400 cm tersebut, dulunya terdapat bangunan-bangunan perwakilan dagang berbagai bangsa: di sebelah utara benteng terdapat bangunan perwakilan dagang Portugis dan Belanda yang dibuka tahun 1607, Inggris (1619), Spanyol (1615), Cina dan Denmark (1618), sedangkan di sebelah timur yaitu di Kampung Mangalekanna dihuni orang-orang suku bangsa Melayu (kompasiana.com).
Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, proyek penggalian di lokasi situs sejarah dapat menghambat kepentingan pengembangan pengetahuan sejarah yang dilakukan arkeolog. Menurut sejarawan Suriadi Mappanganro, keberadaan Benteng Somba Opu dipertahankan bukan saja sebagai bukti perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga perjuangan pengembalian harga diri setelah Gowa dikalahkan pada tahun 1669.
Kegiatan proyek berupa penggalian di sekitar kawasan Somba Opu dapat digolongkan perbuatan merusak situs cagar budaya. Akibat penggalian untuk pembuatan pagar proyek dapat menyebabkan kerusakan sisa benda bersejarah di bawah tanah dan sisa bangunan benteng di lokasi. Konsekwensi dari perbuatan perusakan situs carag budaya adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang No.5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam UU No. 12/2010, pelaku perusakan baik individu maupun kelompok dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana kurungan minimal lima tahun dan denda mulai Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.
Pada dasarnya proyek Gowa Discovery Park yang dilengkapi wahana waterboom sangat bagus untuk wisata kota karena dapat mendatangkan wisatawan asing dan domestik serta terbukanya kesempatan kerja baru. Namun sangat disayangkan penentuan lokasi pembangunannya di kawasan situs sejarah yang dapat menghilangkan jejak sejarah kegemilangan Kerajaan Gowa sebagai Kota Pelabuhan Internasional. Karena itu investor disarankan membangun di luar zona inti Somba Opu. Dalam menentukan zona itu Benteng Somba Opu, investor dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan perlu melibatkan ahli dan peneliti arkeologi.
UU Cagar Budaya
Undang-Undang tentang Cagar Budaya 2010 memiliki paradigma pelestarian dinamis, pengelolaan yang berbasis masyarakat, orientasi kawasan, arkeologi di air, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat semoga dapat mencegah terjadinya perusakan situs benda. UU tentang Cagar Budaya bermakna bahwa yang akan diatur dalam undang-undang ini tidak terbatas hanya benda, tetapi meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan, berdasarkan kriteria, kepemilikan, penguasaan, penemuan, pencarian, pendaftaran, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan. Pengertian warisan budaya, maka dalam UU ini dibatasi terhadap warisan budaya bersifat kebendaan (tangible).
UU tentang Cagar Budaya mengatur sistem register nasional cagar budaya meliputi pendaftaran, peringkat, penetapan, dan penghapusan cagar budaya. Norma ini memberikan tekanan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya aktif dalam pencatatan dan pengelolaan serta pelestarian cagar budaya. Masyarakat juga didorong berperan aktif dalam upaya menjaga pelestarian cagar budaya. UU tentang Cagar Budaya ini juga memuat ketentuan pidana diatur berjenjang berdasarkan klasifikasi tindak pidana, termasuk pula pemberatan pidana pemufakatan jahat, koorporasi, dan pejabat yang melakukan tindak pidana maupun yang memberi perintah tindak pidana, dan hukuman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan.
Munculnya kasus perusakan pada sebagian situs kawasan banteng Somba Opu menjadi ujian dan tantangan penegakan hukum atas UU Cagar Budaya yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2010 dicatatkan dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 130 dan Tambahan LN Nomor 5168: apakah UU ini efektif melindungi dan melestarikan situs cagar budaya seperti benteng Somba Opu atau hanya akan menjadi macan kertas?
(Artikel ini dimuat di harian Fajar Makassar, Selasa, 14 Desember 2010 dengan judul "Gowa Discovery Park Silakan, Tapi Jangan Merusak Situs).
Kelak wahana tersebut berisi: Waterboom, Taman Burung, Taman Gajah, taman olahraga dan bermain, sarana outbond, serta tree top (wahana melintas pohon). Perincian luas wahana taman burung seluas 2 hektare, taman gajah 3 hektare, tree top 2 hektare, dan water boom 3 hektare. Sarana penunjang seperti parkir seluas 2 hektare dengan asumsi jumlah pengunjung pada saat hari raya tetap dapat ditampung serta pembangunan hotel kelas I. Pada wahana taman burung, aneka burung dari berbagai daerah dapat dilihat pengunjung. Wahana tree top disiapkan bagi pengunjung yang hendak menguji nyali, sementara pengunjung yang gemar bermain air disiapkan wahana Water Boom. Proyek pembangunan empat wahana bermain utama rencananya akan rampung dan beroperasi pada Juni 2011.
Dalam desain awal, kawasan Benteng Somba Opu berada di tengah area Gowa Discovery Park. Di dalam area tersebut terdapat sejumlah rumah adat sejumlah kabupaten, seperti rumah adat Toraja dan Bugis. Ada sembilan rumah adat, tidak ada yang kami hilangkan, bahkan kami turut menjaga pemeliharaannya. Investor diharapkan bisa membantu mempublikasikan situs benteng Somba Opu dengan adanya wahana bermain Gowa Discovery agar kawasan Benteng Somba Opu lebih menarik pengunjung. Investor juga menjamin proyek Gowa Discovery tidak akan merusak bangunan cagar budaya yang di dalamnya terdapat rumah adat dari berbagai etnik di Sulawesi Selatan dan Barat itu (tempointeraktif.com). Namun pengamatan beberapa arkeolog menunjukkan adanya kegiatan proyek pada sisi timur ke selatan kawasan benteng yang akan digunakan untuk pembuatan pagar batas kawasan taman burung: mulai dari Baruga Somba Opu sampai ke rumah adat Mamasa.
Proyek Gowa Discovery Park akan dibangun selama satu tahun ke depan. Peletakan batu pertama oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada tanggal 18 Oktober 2010 lalu. Pengelolaan Gowa Discovery Park nantinya dengan sistem bagi hasil selama 30 tahun antara investor 90 persen dengan Pemerintah Sulawesi Selatan sebesar 10 persen. Saat ini proyek pembangunan masih dalam tahap penimbunan di area seluas 10 hektare. Namun pembangunan proyek dinilai melenceng dari rencana awal yang tidak menyentuh cagar budaya. Sebagian batu bata asal abad ke-17 yang dikumpulkan di dekat tembok benteng dijadikan timbunan bangunan baru. Hal inilah yang memantik pada akademisi dan pihak Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Makassar melakukan penolakan dan dihentikan sementara atas rencana pembangunan proyek.
Situs Benteng
Situs Benteng Somba Opu sebelumnya pernah tertimbun selama kurang lebih 300 tahun setelah dihancurkan oleh penjajah Belanda tahun 1669. Pada tahun 1984, situs Benteng Somba Opu berhasil ditemukan kembali dalam eskapasi yang dipimpin oleh Dr.Muchlis Paeni, sejarawan dari UNHAS. Dalam kegiatan awal eskavasi situs Benteng Somba Opu, pihak Japan Fundation ikut memberikan bantuan dana pada masa pemerintahan Gubernur Sulsel, Prof.Dr.H.Ahmad Amiruddin.
Banteng Somba Opu mulai dibangun pada abad XV oleh Raja Gowa ke-9, Karaeng Tumapparrisi Kallonna kemudian dilanjutkan oleh Raja Gowa ke-10, Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Kawasan Benteng Somba Opu ini pada masa-masa kemahsyurannya merupakan salah satu “Kota Dunia” dengan dilengkapi Pelabuhan Internasional yang paling ramai didatangi pedagang-pedagang dari Eropa di Asia Tenggara. Kebesaran Kerajaan Gowa dengan kota kerajaan Benteng Somba Opu merupakan fakta sejarah yang tidak boleh dihapus oleh pembangunan sarana bermain didalam kota modern.
Bentuk benteng Somba Opu secara utuh berbentuk persegi empat berdasarkan peta hasil stilasi yang dibuat oleh Francois Valentijn dan disempurnakan oleh Bleau pada tahun 1638. Di dalam kawasan banteng Somba Opu terdiri dari istana raja, rumah para bangsawan, pembesar dan para pegawai kerajaan. Di luar tembok benteng yang terbuat dari batu padas dan tanah isian dengan ketebalan bervariasi antara 200 – 400 cm tersebut, dulunya terdapat bangunan-bangunan perwakilan dagang berbagai bangsa: di sebelah utara benteng terdapat bangunan perwakilan dagang Portugis dan Belanda yang dibuka tahun 1607, Inggris (1619), Spanyol (1615), Cina dan Denmark (1618), sedangkan di sebelah timur yaitu di Kampung Mangalekanna dihuni orang-orang suku bangsa Melayu (kompasiana.com).
Dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan, proyek penggalian di lokasi situs sejarah dapat menghambat kepentingan pengembangan pengetahuan sejarah yang dilakukan arkeolog. Menurut sejarawan Suriadi Mappanganro, keberadaan Benteng Somba Opu dipertahankan bukan saja sebagai bukti perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga perjuangan pengembalian harga diri setelah Gowa dikalahkan pada tahun 1669.
Kegiatan proyek berupa penggalian di sekitar kawasan Somba Opu dapat digolongkan perbuatan merusak situs cagar budaya. Akibat penggalian untuk pembuatan pagar proyek dapat menyebabkan kerusakan sisa benda bersejarah di bawah tanah dan sisa bangunan benteng di lokasi. Konsekwensi dari perbuatan perusakan situs carag budaya adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang No.5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam UU No. 12/2010, pelaku perusakan baik individu maupun kelompok dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana kurungan minimal lima tahun dan denda mulai Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.
Pada dasarnya proyek Gowa Discovery Park yang dilengkapi wahana waterboom sangat bagus untuk wisata kota karena dapat mendatangkan wisatawan asing dan domestik serta terbukanya kesempatan kerja baru. Namun sangat disayangkan penentuan lokasi pembangunannya di kawasan situs sejarah yang dapat menghilangkan jejak sejarah kegemilangan Kerajaan Gowa sebagai Kota Pelabuhan Internasional. Karena itu investor disarankan membangun di luar zona inti Somba Opu. Dalam menentukan zona itu Benteng Somba Opu, investor dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan perlu melibatkan ahli dan peneliti arkeologi.
UU Cagar Budaya
Undang-Undang tentang Cagar Budaya 2010 memiliki paradigma pelestarian dinamis, pengelolaan yang berbasis masyarakat, orientasi kawasan, arkeologi di air, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat semoga dapat mencegah terjadinya perusakan situs benda. UU tentang Cagar Budaya bermakna bahwa yang akan diatur dalam undang-undang ini tidak terbatas hanya benda, tetapi meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan, berdasarkan kriteria, kepemilikan, penguasaan, penemuan, pencarian, pendaftaran, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan. Pengertian warisan budaya, maka dalam UU ini dibatasi terhadap warisan budaya bersifat kebendaan (tangible).
UU tentang Cagar Budaya mengatur sistem register nasional cagar budaya meliputi pendaftaran, peringkat, penetapan, dan penghapusan cagar budaya. Norma ini memberikan tekanan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya aktif dalam pencatatan dan pengelolaan serta pelestarian cagar budaya. Masyarakat juga didorong berperan aktif dalam upaya menjaga pelestarian cagar budaya. UU tentang Cagar Budaya ini juga memuat ketentuan pidana diatur berjenjang berdasarkan klasifikasi tindak pidana, termasuk pula pemberatan pidana pemufakatan jahat, koorporasi, dan pejabat yang melakukan tindak pidana maupun yang memberi perintah tindak pidana, dan hukuman pidananya ditambah 1/3 dari ketentuan.
Munculnya kasus perusakan pada sebagian situs kawasan banteng Somba Opu menjadi ujian dan tantangan penegakan hukum atas UU Cagar Budaya yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2010 dicatatkan dalam Lembaran Negara (LN) Nomor 130 dan Tambahan LN Nomor 5168: apakah UU ini efektif melindungi dan melestarikan situs cagar budaya seperti benteng Somba Opu atau hanya akan menjadi macan kertas?
(Artikel ini dimuat di harian Fajar Makassar, Selasa, 14 Desember 2010 dengan judul "Gowa Discovery Park Silakan, Tapi Jangan Merusak Situs).
8/22/2010
Kebijakan Pelestarian Gedung Tua Bersejarah
Pada berbagai kota bersejarah di Indonesia, bangunan-bangunan tua bersejarah banyak yang telah berubah fungsi dan berubah wajah. Seperti wacana renovasi Benteng Fort Rotterdam di Makassar yang dikenal nama Benteng Panynyua memantik reaksi dari masyarakat. Masyarakat kontan mengorganisasi diri dalam komunitas peduli bangunan tua yang dipelopori Triyatni, Muslimin Beta, Misbah serta beberapa wartawan seperti Andi Aisyah Lamboge, Ken Angel dan Arini dengan dukungan penuh dari masyarakat seniman seperti Syahrial Tato dan masyarakat internasional seperti Dr Christian (seorang sejarawan dari Belanda) bersama istrinya Sunarti Tutu dan antropolog dari Italia, Alesandro.
Dasar argumentasi pemerintah pada berbagai kota adalah pertimbangan kualitas bangunan menyangkut nilai ekonomi serta fungsional bangunan berbanding dengan kebutuhan ruang. Bangunan tua yang tidak ekonomis banyak yang sudah disulap menjadi bangunan perkantoran modern atau ruko (rumah toko) dengan motif-motif ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pendidikan sejarah. Ini adalah dampak pembangunan kota menuju ke arah modernitas yang secara tidak langsung berdampak pada pola pikir yang praktis dan pragmatis.
Perubahan wajah dan fungsi akibat gerusan pembangunan modern namun mengabaikan sejarah yang tercermin dari keberadaan bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai sejarah. Bagi sebagian pemerintah daerah, keberadaan bangunan kuno dan gedung tua dipandang sebagai “sampah” kota bahkan mirip penyakit kota yang harus dilenyapkan.
Sejak dekade 1960-an hingga dekade 1990-an, wacana pelestarian bangunan dan gedung tua (cagar budaya) sebenarnya sudah menjadi wacana masyarakat internasional. Fakta tersebut dapat kita saksikan dengan adanya beberapa dokumen penting berupa piagam pelestarian bangunan tua, diantaranya, The Venice Charter (1964-1965), The Burra Charter (1979), Rekomendasi UNESCO (1976), Piagam Washington (1987), serta The World Herritage Cities Management Guide (1991). Sementara di Indonesia telah ada dokumen pelestarian bangunan tua bernama Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan beberapa tahun lalu.
Banyak warisan arsitektural dari bangunan tua utamanya bangunan peninggalan kolonial di Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan dalam hal seni bangunan dan teknik arsitektural. Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Bila UU No. 5/1992 mempertegas perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah, sementara UU No 28/2002 membuka peluang bagi pemanfaatan gedung bagi kepentingan ekonomis. Bila keberadaan bangunan tua itu berada di daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski banyak disesalkan oleh pemerhati sejarah dan beberapa komunitas masyarakat pencinta bangunan tua, mereka tidak banyak berbuat karena kurangnya pengetahuan landasan dan caranya merubah pola pikir pejabat pemerintah berwenang. Padahal bangunan-bangunan tua, apalagi bangunan tua bersejarah secara konsepsional telah mendapat perlindungan melalui kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti contohnya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.
Pada Pasal 1 ayat {1} dalam UU ini, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah dibagi atas dua: pertama, benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yangberupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yangberumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yangkhas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dankebudayaan; kedua, benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan , dan kebudayaan. Sementara pada ayat {2} menyatakan bahwa Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
UU No. 5/1992 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci mengatur perlindungan bangunan tua yang masuk kategori benda cagar budaya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992. Pada Bab V Pasal 22 hingga Pasal 27 termaktub rincian aturan menyangkut perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Pada Pasal 22 menyebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasai.
Sementara pada Pasal 23 yang terdiri dari tiga ayat menyebutkan bahwa (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelematan, pengamanan, perawatan dan pemugaran; (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan; (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat {2} ditetapkan dengan system permintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan. Sedang Pasal 24 tertulis bahwa dalam rangka pelestarian benda cagar budaya Menteri menetapkan situs; (2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tantangan Kebijakan
Dari segi kebijakan, tantangan terhadap benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2005. Mengacu pada Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung (PPBG), seluruh bangunan gedung harus layak fungsi pada tahun 2010.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) disahkan pada tanggal 16 Desember 2002, terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Pada umumnya, undang-undang ini mengatur tentang ketentuan bangunan gedung yang meliputi persyaratan bangunan gedung, fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan.
Bahkan disebutkan bahwa pemilik bangunan yang melanggar persyaratan teknis bangunan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran bangunan gedung. Selain itu retribusi pelayanan pemberian Izin Memiliki Bangunan (IMB) merupakan retribusi golongan perizinan tertentu. Dan komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi peninjauan desain atau gambar, pemantauan pelaksanaan pembangunan. Pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
Berdasarkan argumentasi pemerintah, UU No. 28 tahun 2002 dibuat dengan tujuan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan efisien, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, terwujudnya kepastian hukum gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Undang-undang bangunan gedung (UUBG) mengandung fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan dan sanksi.
Dari website resmi pemerintah berwenang, pokok pikiran (latar belakang) disusunnya UUBG antara lain bangunan gedung mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk watak, perwujudan, produktivitas dan jati diri manusia; untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu adanya peraturan yang bersifat rasional sebagai payung dalam pengaturan bangunan gedung dan lingkungannya; dengan OTDA, pemda menjadi sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di daerah; perkembangan pembangunan gedung; perkembangan pembangunan gedung dalam 2 dasawarsa terakhir sangat pesat, namun belum ada jaminan terwujudnya bagunan gedung yang fungsional, efisien serta tertib dalam pembangunannya; era terbuka dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
Dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (UUBG 2002), mengatur juga tentang bangunan tinggi dan jaminan keselamatan bagi penghuni bangunan tinggi. Pada bangunan tinggi, faktor keselamatan penghuni bangunan tinggi telah menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan keselamatan gedung yang sangat penting adalah kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
Persoalan persyaratan keselamatan gedung ini adalah salah satu kelemahan dari bangunan tua sehingga berpotensi dimusnahkan oleh kebijakan UU No. 28/2002. Inilah tantangan nyata bagi komunitas peduli bangunan tua dari aspek kebijakan. Karena itu, advokasi kebijakan layak dipertimbangkan komunitas peduli bangunan tua untuk dilakukan secara simultan dengan kegiatan-kegiatan teknis lainnya seperti kegiatan mengidentifikasi bangunan tua di seantero kota. (Artikel ini dimuat pada Tribun Timur, Selasa, 03 Agustus 2010)
Dasar argumentasi pemerintah pada berbagai kota adalah pertimbangan kualitas bangunan menyangkut nilai ekonomi serta fungsional bangunan berbanding dengan kebutuhan ruang. Bangunan tua yang tidak ekonomis banyak yang sudah disulap menjadi bangunan perkantoran modern atau ruko (rumah toko) dengan motif-motif ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pendidikan sejarah. Ini adalah dampak pembangunan kota menuju ke arah modernitas yang secara tidak langsung berdampak pada pola pikir yang praktis dan pragmatis.
Perubahan wajah dan fungsi akibat gerusan pembangunan modern namun mengabaikan sejarah yang tercermin dari keberadaan bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai sejarah. Bagi sebagian pemerintah daerah, keberadaan bangunan kuno dan gedung tua dipandang sebagai “sampah” kota bahkan mirip penyakit kota yang harus dilenyapkan.
Sejak dekade 1960-an hingga dekade 1990-an, wacana pelestarian bangunan dan gedung tua (cagar budaya) sebenarnya sudah menjadi wacana masyarakat internasional. Fakta tersebut dapat kita saksikan dengan adanya beberapa dokumen penting berupa piagam pelestarian bangunan tua, diantaranya, The Venice Charter (1964-1965), The Burra Charter (1979), Rekomendasi UNESCO (1976), Piagam Washington (1987), serta The World Herritage Cities Management Guide (1991). Sementara di Indonesia telah ada dokumen pelestarian bangunan tua bernama Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan beberapa tahun lalu.
Banyak warisan arsitektural dari bangunan tua utamanya bangunan peninggalan kolonial di Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan dalam hal seni bangunan dan teknik arsitektural. Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Bila UU No. 5/1992 mempertegas perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah, sementara UU No 28/2002 membuka peluang bagi pemanfaatan gedung bagi kepentingan ekonomis. Bila keberadaan bangunan tua itu berada di daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski banyak disesalkan oleh pemerhati sejarah dan beberapa komunitas masyarakat pencinta bangunan tua, mereka tidak banyak berbuat karena kurangnya pengetahuan landasan dan caranya merubah pola pikir pejabat pemerintah berwenang. Padahal bangunan-bangunan tua, apalagi bangunan tua bersejarah secara konsepsional telah mendapat perlindungan melalui kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti contohnya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya.
Pada Pasal 1 ayat {1} dalam UU ini, yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah dibagi atas dua: pertama, benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yangberupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yangberumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yangkhas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dankebudayaan; kedua, benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan , dan kebudayaan. Sementara pada ayat {2} menyatakan bahwa Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
UU No. 5/1992 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci mengatur perlindungan bangunan tua yang masuk kategori benda cagar budaya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992. Pada Bab V Pasal 22 hingga Pasal 27 termaktub rincian aturan menyangkut perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Pada Pasal 22 menyebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasai.
Sementara pada Pasal 23 yang terdiri dari tiga ayat menyebutkan bahwa (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelematan, pengamanan, perawatan dan pemugaran; (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan; (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat {2} ditetapkan dengan system permintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan. Sedang Pasal 24 tertulis bahwa dalam rangka pelestarian benda cagar budaya Menteri menetapkan situs; (2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tantangan Kebijakan
Dari segi kebijakan, tantangan terhadap benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2005. Mengacu pada Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung (PPBG), seluruh bangunan gedung harus layak fungsi pada tahun 2010.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) disahkan pada tanggal 16 Desember 2002, terdiri dari 10 bab dan 49 pasal. Pada umumnya, undang-undang ini mengatur tentang ketentuan bangunan gedung yang meliputi persyaratan bangunan gedung, fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan.
Bahkan disebutkan bahwa pemilik bangunan yang melanggar persyaratan teknis bangunan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pembongkaran bangunan gedung. Selain itu retribusi pelayanan pemberian Izin Memiliki Bangunan (IMB) merupakan retribusi golongan perizinan tertentu. Dan komponen biaya perhitungan retribusi IMB meliputi peninjauan desain atau gambar, pemantauan pelaksanaan pembangunan. Pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
Berdasarkan argumentasi pemerintah, UU No. 28 tahun 2002 dibuat dengan tujuan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan efisien, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, terwujudnya kepastian hukum gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Undang-undang bangunan gedung (UUBG) mengandung fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan dan sanksi.
Dari website resmi pemerintah berwenang, pokok pikiran (latar belakang) disusunnya UUBG antara lain bangunan gedung mempunyai peran sangat strategis dalam membentuk watak, perwujudan, produktivitas dan jati diri manusia; untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu adanya peraturan yang bersifat rasional sebagai payung dalam pengaturan bangunan gedung dan lingkungannya; dengan OTDA, pemda menjadi sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di daerah; perkembangan pembangunan gedung; perkembangan pembangunan gedung dalam 2 dasawarsa terakhir sangat pesat, namun belum ada jaminan terwujudnya bagunan gedung yang fungsional, efisien serta tertib dalam pembangunannya; era terbuka dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
Dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (UUBG 2002), mengatur juga tentang bangunan tinggi dan jaminan keselamatan bagi penghuni bangunan tinggi. Pada bangunan tinggi, faktor keselamatan penghuni bangunan tinggi telah menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan keselamatan gedung yang sangat penting adalah kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
Persoalan persyaratan keselamatan gedung ini adalah salah satu kelemahan dari bangunan tua sehingga berpotensi dimusnahkan oleh kebijakan UU No. 28/2002. Inilah tantangan nyata bagi komunitas peduli bangunan tua dari aspek kebijakan. Karena itu, advokasi kebijakan layak dipertimbangkan komunitas peduli bangunan tua untuk dilakukan secara simultan dengan kegiatan-kegiatan teknis lainnya seperti kegiatan mengidentifikasi bangunan tua di seantero kota. (Artikel ini dimuat pada Tribun Timur, Selasa, 03 Agustus 2010)
7/30/2010
Komisi Informasi dan Hak Memperoleh Informasi
UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) telah berlaku sejak 30 April 2010. Awalnya, bernama RUU tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan diprakarsai oleh komponen masyarakat sipil yang diusulkan kepada DPR RI dan Pemerintah pada tahun 2002. Beberapa daerah telah membentuk Komisi Informasi Propinsi setelah Komisi Informasi Pusat telah terbentuk pada tahun 2009 silam.
Secara konstitusional, Hak kebebasan untuk memperoleh informasi publik telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998. Pada Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD RI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia mengatur, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh sebab itu, UU KIP dirumuskan atas dasar pemikiran bahwa informasi adalah hak dasar semua orang, dan sejalan dengan rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebut diatas.
Secara filosofis, UU Keterbukaan Informasi Publik bermaksud untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) agar pemerintahan bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Dengan adanya keterbukaan bagi penyelenggara negara dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan-tindakan menyimpang yang dapat merugikan orang banyak (public). Keterbukaan akan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat publik.
UU Keterbukaan Informasi Publik menuntut pemerintah dan badan-badan public untuk selalu bertindak accountable dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Pendekatan budaya keterbukaan (transparency culture) lambat laun diharapkan dapat mengikis praktek KKN karena pada dasarnya KKN tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendekatan represif berupa penegakan hukum.
Karena itu adalah hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi (freedom of information) pada instansi pemerintah maupun badan-badan publik lainnya dijamin melalui UU No 14/2008. Hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi memiliki relevansi terhadap peningkatan kualitas pelibatan masyarakat (public involvement) dalam proses pengambilan kebijakan publik. Apabila tanpa jaminan kemudahan memperoleh informasi, pelibatan masyarakat tidak banyak berarti (meaningless).
Hak atas akses informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin baik dalam ketentuan internasional maupun nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menegaskan adanya hak setiap orang untuk mencari, menerima dan memberikan informasi atau kalimat aslinya berbunyi, “Everyone has the right to opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. Demikian pula pada Pasal 19 Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik mengatur hal serupa. Sebagaimana diketahui, Kovenan Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi ke dalam UU No. 12/2005.
Dengan berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat Indonesia tidak lagi terikat dengan UU No. 7/1971 tentang Kearsipan yang bertentangan secara diametral terhadap kebebasan akses informasi publik. UU produk Orde Baru tersebut mengkriminalkan dengan ancaman penjara selama 20 tahun apabila memberitahukan isi naskah dan dokumen yang digolongkan rahasia kepada pihak ketiga.
Sebelum diundangkannya UU KIP, sebenarnya telah ada peraturan perundangan yang mengatur tata cara meminta informasi publik pada penyelenggara negara yakni Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam PP ini, klausul yang berhubungan dengan akses informasi publik antara lain diatur pada Bab II Pasal 2, Bab III Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10.
Dalam Pasal 2 ayat (1), PP ini telah diatur, antara lain bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara. Sementara Pasal 3 PP ini berbunyi : (1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimasud dalam pasal (2) ayat {1} huruf a, maka yang berkepentingan berhak menyatakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait; (2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya, Pasal 4 PP No. 68 Tahun 1999 juga menyatakan, bahwa pemberian informasi sebagai hak masyarakat dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau komisi Pemeriksa. Namun pemberian informasi haruslah disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai: (1) Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan potokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; (2) Keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan (3) Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. Sedangkan Pasal 10 PP ini menyatakan, bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi Informasi
UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPR untuk tingkat Pusat dan DPRD tingkat propinsi. Komisi Informasi memiliki fungsi umum dan fungsi khusus; fungsi umum berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini sedangkan fungsi khusus melakukan penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan UU ini dan membina sistem penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik.
Berkaitan dengan fungsi khusus penyelesaian sengketa, Komisi Infomasi menjalankan fungsinya pada level kedua, apabila atasan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan informasi (internal reviewer) tidak berhasil menjalankan tugasnya. Jadi disini, Komisi Informasi bersifat external reviewer berdasar pada pengaduan dari masyarakat.
Pejabat penyedia informasi dapat diberikan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara apabila bermaksud menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Adanya ancama hukuman pada UU ini dengan maksud mempercepat perubahan sikap mental para birokrat pemerintah dan pengelola badan-badan publik agar bersikap terbuka terhadap masyarakat yang menginginkan informasi. Pejabat penyedia informasi yang menghambat akses informasi yang menyangkut kepentingan publik dapat dikategorikan melakukan kejahatan publik sehingga dapat diganjar dengan ancaman penjara setelah kasusnya diproses oleh Komisi Informasi.
Terkait dengan hukum pidana pada UU KIP, Agus Sahat Lumban (2004) dalam thesisnya pada Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang mengatakan, dalam hal perbuatan dan sanksi pidana yang diancamkan, maka kriminalisasi dari perbuatan-perbuatan tertentu seharusnya sesuai dengan aspek-aspek tujuan pemidanaan dan sesuai dengan UUD 1945 dan TAP MPR yang mengatur perlindungan HAM. Khusus mengenai sanksi pidana, seharusnya dirumuskan dalam bentuk yang cermat, jelas dalam menentukan berat ringannya sanksi, serta disusun dalam suatu pola yang seragam.
Sehubungan dengan diskursus tentang Komisi Informasi, saat ini pemerintah provinsi bersama DPRD Propinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaringannya oleh sebuah tim seleksi yang diketuai Prof Drs. Sadly, MPA dan telah memasuki penyaringan tingkat kedua berupa seleksi tes tertulis. Semoga tim seleksi KIP bertindak profesional dan pihak DPRD Propinsi Sulsel dapat memilih komisioner Komisi Informasi Provinsi yang kompeten dibidang ini (Dimuat di Harian Fajar, Rabu, 28 Juli 2010).
Penulis, Muslimin B. Putra, Calon Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Secara konstitusional, Hak kebebasan untuk memperoleh informasi publik telah mendapatkan pengakuan dalam UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998. Pada Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD RI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia mengatur, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh sebab itu, UU KIP dirumuskan atas dasar pemikiran bahwa informasi adalah hak dasar semua orang, dan sejalan dengan rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebut diatas.
Secara filosofis, UU Keterbukaan Informasi Publik bermaksud untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) agar pemerintahan bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Dengan adanya keterbukaan bagi penyelenggara negara dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan-tindakan menyimpang yang dapat merugikan orang banyak (public). Keterbukaan akan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat publik.
UU Keterbukaan Informasi Publik menuntut pemerintah dan badan-badan public untuk selalu bertindak accountable dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Pendekatan budaya keterbukaan (transparency culture) lambat laun diharapkan dapat mengikis praktek KKN karena pada dasarnya KKN tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendekatan represif berupa penegakan hukum.
Karena itu adalah hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi (freedom of information) pada instansi pemerintah maupun badan-badan publik lainnya dijamin melalui UU No 14/2008. Hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi memiliki relevansi terhadap peningkatan kualitas pelibatan masyarakat (public involvement) dalam proses pengambilan kebijakan publik. Apabila tanpa jaminan kemudahan memperoleh informasi, pelibatan masyarakat tidak banyak berarti (meaningless).
Hak atas akses informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin baik dalam ketentuan internasional maupun nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menegaskan adanya hak setiap orang untuk mencari, menerima dan memberikan informasi atau kalimat aslinya berbunyi, “Everyone has the right to opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. Demikian pula pada Pasal 19 Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik mengatur hal serupa. Sebagaimana diketahui, Kovenan Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi ke dalam UU No. 12/2005.
Dengan berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat Indonesia tidak lagi terikat dengan UU No. 7/1971 tentang Kearsipan yang bertentangan secara diametral terhadap kebebasan akses informasi publik. UU produk Orde Baru tersebut mengkriminalkan dengan ancaman penjara selama 20 tahun apabila memberitahukan isi naskah dan dokumen yang digolongkan rahasia kepada pihak ketiga.
Sebelum diundangkannya UU KIP, sebenarnya telah ada peraturan perundangan yang mengatur tata cara meminta informasi publik pada penyelenggara negara yakni Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam PP ini, klausul yang berhubungan dengan akses informasi publik antara lain diatur pada Bab II Pasal 2, Bab III Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10.
Dalam Pasal 2 ayat (1), PP ini telah diatur, antara lain bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara. Sementara Pasal 3 PP ini berbunyi : (1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimasud dalam pasal (2) ayat {1} huruf a, maka yang berkepentingan berhak menyatakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait; (2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya, Pasal 4 PP No. 68 Tahun 1999 juga menyatakan, bahwa pemberian informasi sebagai hak masyarakat dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau komisi Pemeriksa. Namun pemberian informasi haruslah disertai data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai: (1) Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan potokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; (2) Keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan (3) Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. Sedangkan Pasal 10 PP ini menyatakan, bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi Informasi
UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPR untuk tingkat Pusat dan DPRD tingkat propinsi. Komisi Informasi memiliki fungsi umum dan fungsi khusus; fungsi umum berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ini sedangkan fungsi khusus melakukan penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan UU ini dan membina sistem penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik.
Berkaitan dengan fungsi khusus penyelesaian sengketa, Komisi Infomasi menjalankan fungsinya pada level kedua, apabila atasan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan informasi (internal reviewer) tidak berhasil menjalankan tugasnya. Jadi disini, Komisi Informasi bersifat external reviewer berdasar pada pengaduan dari masyarakat.
Pejabat penyedia informasi dapat diberikan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara apabila bermaksud menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Adanya ancama hukuman pada UU ini dengan maksud mempercepat perubahan sikap mental para birokrat pemerintah dan pengelola badan-badan publik agar bersikap terbuka terhadap masyarakat yang menginginkan informasi. Pejabat penyedia informasi yang menghambat akses informasi yang menyangkut kepentingan publik dapat dikategorikan melakukan kejahatan publik sehingga dapat diganjar dengan ancaman penjara setelah kasusnya diproses oleh Komisi Informasi.
Terkait dengan hukum pidana pada UU KIP, Agus Sahat Lumban (2004) dalam thesisnya pada Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang mengatakan, dalam hal perbuatan dan sanksi pidana yang diancamkan, maka kriminalisasi dari perbuatan-perbuatan tertentu seharusnya sesuai dengan aspek-aspek tujuan pemidanaan dan sesuai dengan UUD 1945 dan TAP MPR yang mengatur perlindungan HAM. Khusus mengenai sanksi pidana, seharusnya dirumuskan dalam bentuk yang cermat, jelas dalam menentukan berat ringannya sanksi, serta disusun dalam suatu pola yang seragam.
Sehubungan dengan diskursus tentang Komisi Informasi, saat ini pemerintah provinsi bersama DPRD Propinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaringannya oleh sebuah tim seleksi yang diketuai Prof Drs. Sadly, MPA dan telah memasuki penyaringan tingkat kedua berupa seleksi tes tertulis. Semoga tim seleksi KIP bertindak profesional dan pihak DPRD Propinsi Sulsel dapat memilih komisioner Komisi Informasi Provinsi yang kompeten dibidang ini (Dimuat di Harian Fajar, Rabu, 28 Juli 2010).
Penulis, Muslimin B. Putra, Calon Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
7/12/2010
Menanti Komisi Informasi Daerah Sulawesi Selatan
Prinsip transparansi adalah salah satu pilar perwujudan good governance. Pemberlakukan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengemban misi transparansi penyelenggara negara dan badan-badan publik di seluruh Indonesia. Dengan adanya UU KIP yang efektif berlaku sejak 30 April 2010, warga negara dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, agenda kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Dengan demikian, akan tercipta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui transparansi informasi di lingkungan Badan Publik. Melalui UU KIP, masyarakat dijamin oleh UU untuk memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik terkait penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.
Yang dimaksud badan publik berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan informasi publik menurut UU ini (Pasal 1 ayat 2) adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Komisi Informasi merupakan amanah dari UU KIP yang akan memantau dan mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 4 UU No 14/2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pada tingkat pusat, Komisi Informasi (selanjutnya disebut KI Pusat) telah terbentuk melalui Keputusan Presiden No 48/P Tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009. KI Pusat berjumlah 7 orang komisioner terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM). Dari tujuh komisioner, dua orang dari unsur pemerintah dan selebihnya lima orang dari unsur masyarakat.
Sesuai dengan UU KIP, KI Pusat dan Daerah dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
Keterbukaan Informasi di Daerah
Praktek transparansi informasi publik sebenarnya sudah diterapkan pada beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia melalui payung hukum paraturan daerah (perda) transparansi. Misalnya, di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan telah dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi meski belum ada kajian dari lembaga yang kompeten yang bisa mengevaluasi efektifitas kinerja lembaga ini dan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya.
Berbeda dengan praktek transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Abdul Rahman Ma'mun (komisioner KI Pusat), praktik keterbukaan informasi di Kabupaten Lebak telah memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal, dengan APBD terendah se-Provinsi Banten ini. Sebelum adanya Perda Transparansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak awal tahun 2004 hanya Rp 11 miliar. Dalam jangka 9 bulan menjadi Rp 20 miliar, bahkan di tahun 2006 PAD Kabupaten Lebak menjadi Rp 32 miliar.
Demikian pula di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan SK Bupati No 17/2002. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk mempraktikkan keterbukaan informasi publik dalam hal perizinan. Hasilnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha meningkat karena mengurus izin menjadi mudah, cepat, dan biaya ringan. Jumlah perusahaan berkembang pesat dari 6.373 perusahaan (2002) menjadi 8.105 perusahaan (2005). Dampaknya angka tenaga kerja di sektor industri naik menjadi 46.794 orang (2005) dari 40.785 orang (2002). Investasi pun meningkat hingga 61,3 persen dalam waktu 3 tahun (2002-2005) (Ma'mun, 2009).
Komisi Informasi Daerah
Komisi Informasi Pusat (KIP) menargetkan pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) di beberapa provinsi pada 2010. Ada 9 (Sembilan) provinsi yang menjadi prioritas membentuk KID yaitu Sulawesi Selatan, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bali, Gorontalo dan Kalimantan Timur. Hingga Mei 2010, baru dua provinsi memiliki komisi informasi yakni, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tugas Komisi Informasi sesuai UU KIP adalah menyusun standarisasi pelayanan informasi publik bagi badan publik, baik badan publik negara yang didanai APBN atau APBD seperti departemen, DPR, DPRD, pemerintah daerah, maupun badan publik non-negara yang mendapat dana masyarakat atau luar negeri, seperti yayasan, sekolah, perguruan tinggi atau LSM. Dalam UU ini dikecualikan 10 macam yang tidak termasuk kategori informasi publik diantaranya, kandungan kekayaan alam, sistem pertahanan, hal yang bersifat pribadi. Komisi ini berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara peminta informasi dengan badan-badan publik. Tentang standar layanan informasi publik, KI Pusat telah berhasil menyusunnya dan tertuang dalam Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010.
Selain itu, Komisi Informasi menyusun pengelompokan informasi, diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya BMKG wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.
Dalam UU KIP, badan publik yang tidak menyiapkan informasi publik dalam 17 hari, berhak dilaporkan ke atasannya. Jika tidak tanggapan dari pejabat yang berwenang dalam 30 hari maka harus dilaporkan ke komisi informasi untuk memediasi dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Setiap badan publik yang terbukti tidak memberikan satu informasi publik akan diancam pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 5 juta.
Dalam menjalankan tugasnya dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan pelayanan informasi, dan pemenuhan hak warga negara memperoleh akses informasi publik, Komisi Informasi dapat bekerjasama dengan lembaga mandiri lainnya yakni Ombudsman Republik Indonesia atau biasa disebut Ombudsman. Lembaga mandiri ini terbentuk melalui UU No. 37/2008 yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Berdasarkan perintah kedua UU, Ombudsman bertugas pada pengawasan pelayanan publik sedangkan Komisi Informasi mengawasi pelayanan informasi publik. Dalam praktek pelayanan publik yang tidak memuaskan biasanya disebabkan oleh kurang perangkat informasi dari para penyelenggara layanan publik, termasuk dari badan publik.
(Dimuat di Tribun Timur, Senin, 12 Juli 2010)
Dengan demikian, akan tercipta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui transparansi informasi di lingkungan Badan Publik. Melalui UU KIP, masyarakat dijamin oleh UU untuk memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik terkait penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.
Yang dimaksud badan publik berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan informasi publik menurut UU ini (Pasal 1 ayat 2) adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Komisi Informasi merupakan amanah dari UU KIP yang akan memantau dan mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 4 UU No 14/2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pada tingkat pusat, Komisi Informasi (selanjutnya disebut KI Pusat) telah terbentuk melalui Keputusan Presiden No 48/P Tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009. KI Pusat berjumlah 7 orang komisioner terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM). Dari tujuh komisioner, dua orang dari unsur pemerintah dan selebihnya lima orang dari unsur masyarakat.
Sesuai dengan UU KIP, KI Pusat dan Daerah dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
Keterbukaan Informasi di Daerah
Praktek transparansi informasi publik sebenarnya sudah diterapkan pada beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia melalui payung hukum paraturan daerah (perda) transparansi. Misalnya, di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan telah dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi meski belum ada kajian dari lembaga yang kompeten yang bisa mengevaluasi efektifitas kinerja lembaga ini dan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya.
Berbeda dengan praktek transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Menurut Abdul Rahman Ma'mun (komisioner KI Pusat), praktik keterbukaan informasi di Kabupaten Lebak telah memberi kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah yang sebelumnya merupakan daerah tertinggal, dengan APBD terendah se-Provinsi Banten ini. Sebelum adanya Perda Transparansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak awal tahun 2004 hanya Rp 11 miliar. Dalam jangka 9 bulan menjadi Rp 20 miliar, bahkan di tahun 2006 PAD Kabupaten Lebak menjadi Rp 32 miliar.
Demikian pula di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan SK Bupati No 17/2002. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk mempraktikkan keterbukaan informasi publik dalam hal perizinan. Hasilnya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha meningkat karena mengurus izin menjadi mudah, cepat, dan biaya ringan. Jumlah perusahaan berkembang pesat dari 6.373 perusahaan (2002) menjadi 8.105 perusahaan (2005). Dampaknya angka tenaga kerja di sektor industri naik menjadi 46.794 orang (2005) dari 40.785 orang (2002). Investasi pun meningkat hingga 61,3 persen dalam waktu 3 tahun (2002-2005) (Ma'mun, 2009).
Komisi Informasi Daerah
Komisi Informasi Pusat (KIP) menargetkan pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) di beberapa provinsi pada 2010. Ada 9 (Sembilan) provinsi yang menjadi prioritas membentuk KID yaitu Sulawesi Selatan, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bali, Gorontalo dan Kalimantan Timur. Hingga Mei 2010, baru dua provinsi memiliki komisi informasi yakni, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tugas Komisi Informasi sesuai UU KIP adalah menyusun standarisasi pelayanan informasi publik bagi badan publik, baik badan publik negara yang didanai APBN atau APBD seperti departemen, DPR, DPRD, pemerintah daerah, maupun badan publik non-negara yang mendapat dana masyarakat atau luar negeri, seperti yayasan, sekolah, perguruan tinggi atau LSM. Dalam UU ini dikecualikan 10 macam yang tidak termasuk kategori informasi publik diantaranya, kandungan kekayaan alam, sistem pertahanan, hal yang bersifat pribadi. Komisi ini berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara peminta informasi dengan badan-badan publik. Tentang standar layanan informasi publik, KI Pusat telah berhasil menyusunnya dan tertuang dalam Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010.
Selain itu, Komisi Informasi menyusun pengelompokan informasi, diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencana anggaran badan publik dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Contohnya BMKG wajib menginformasikan prediksi bencana tsunami pasca gempa kepada masyarakat. Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Contohnya informasi tentang prosedur pelayanan publik dan tarif. Keempat, informasi yang dikecualikan atau yang dikategorikan rahasia (pasal 17 UU KIP). Contohnya informasi yang dapat mengganggu penyidikan, seperti informasi rencana penggerebekan teroris, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang bias menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat atau informasi yang bersifat pribadi.
Dalam UU KIP, badan publik yang tidak menyiapkan informasi publik dalam 17 hari, berhak dilaporkan ke atasannya. Jika tidak tanggapan dari pejabat yang berwenang dalam 30 hari maka harus dilaporkan ke komisi informasi untuk memediasi dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Setiap badan publik yang terbukti tidak memberikan satu informasi publik akan diancam pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 5 juta.
Dalam menjalankan tugasnya dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan pelayanan informasi, dan pemenuhan hak warga negara memperoleh akses informasi publik, Komisi Informasi dapat bekerjasama dengan lembaga mandiri lainnya yakni Ombudsman Republik Indonesia atau biasa disebut Ombudsman. Lembaga mandiri ini terbentuk melalui UU No. 37/2008 yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Berdasarkan perintah kedua UU, Ombudsman bertugas pada pengawasan pelayanan publik sedangkan Komisi Informasi mengawasi pelayanan informasi publik. Dalam praktek pelayanan publik yang tidak memuaskan biasanya disebabkan oleh kurang perangkat informasi dari para penyelenggara layanan publik, termasuk dari badan publik.
(Dimuat di Tribun Timur, Senin, 12 Juli 2010)
2/23/2010
Kisah Kerbau dan Sang Presiden
Dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini diwarnai dengan metaphor binatang. Bila sebelumnya ramai dibicarakan binatang cicak, buaya, gurita, maka kali ini tentang kerbau. Pangkal munculnya perbincangan tentang kerbau dalam wacana politik ketika sebuah aksi demonstrasi mengkritisi program 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono di kawasan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (28/01/2010) dengan membawa serta binatang kerbau yang bertuliskan “Si Buya” pada badan kerbau.
Binatang kerbau termasuk dalam sub-family Bovinae, dan genus Buballus. Kerbau yang ada di wilayah Indonesia dikenal ada dua jenis yakni: pertama, kerbau sungai (River Buffalo) yang mempunyai 48 kromosom (24 pasang kromosom), misalnya kerbau Murrah yang ada di Sumatera Utara; dan kedua, kerbau lumpur atau rawa (Swap Buffalo) yang mempunyai 50 kromosom (24 pasang kromosom). Jenis kedualah yang paling banyak populasinya karena jenis kerbau pekerja dan penghasil daging, sedang jenis pertama adalah penghasil susu perah populasinya sangat sedikit. Dari seluruh populasi kerbau di seluruh dunia, hanya 2 persen yang berada di Indonesia.
Meski populasinya hanya dua persen, berita tentang kerbau Indonesia telah menyebar luas ke seluruh dunia sehubungan dengan demonstrasi kerbau “Si Buya” di depan Istana Negara. Tulisan “Si Buya” tersebutlah yang menjadi pemicu Presiden SBY tersindir dan menjadi perbincangan para petinggi negara ketika melangsungkan hajatan kenegaraan bersama semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat pada Selasa (02/2/2010).
Reaksi Presiden SBY tersebut seakan menjadi pemantik dimulainya polemik tentang persoalan etika dalam berdemonstrasi. Bagi para pendukung SBY, demonstrasi dengan melibatkan kerbau sangat tidak etis. Apalagi binatang kerbau bagi masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai symbol kebodohan dan kelambanan. Berbeda dengan astrologi orang China yang melambangkan kerbau sebagai simbol kehebatan. Pihak kepolisian pun kesulitan menangkap demonstran yang membawa binatang karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Bila menggunakan tuduhan pencemaran nama dengan adanya nama “Si Buya” sangat tidak beralasan, kecuali bila bertuliskan “Si Buyo” maka bisa saja dijadikan akronim “Susilo Bambang Yudhoyono”.
Sebenarnya masyarakat tidak banyak yang menaruh perhatian kehadiran kerbau dalam aksi demonstrasi pada 28 Januari. Namun SBY sendiri yang mempopulerkan kehadiran kerbau dalam demonstrasi dan mendapatkan liputan media massa secara luas. Sepertinya scenario mengangkat demonstrasi kerbau “Si Buya” untuk mencitrakan dirinya yang kembali teraniaya sehingga public kembali berpihak kepadanya. Namun bukannya citra positif yang didapat, justru public semakin mempertegas imaji tentang sosok pribadi SBY yang sebenarnya sebagai sosok melankolis yang doyan mengeluh.
Pendukung Presiden SBY pun tidak bisa secara langsung mengajukan pasal-pasal pidana kepada para demonstran itu. Penyebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir norma tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2006 dalam putusannya No. 022/PUU-IV/2006. Namun MK tidak menganulir penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakil negara asing di Indonesia. Bagi para penghina kepala negara asing, ancaman pidananya sangat berat maksimun 5 tahun. Memang harus diakui bahwa dampak putusan tersebut menyebabkan berkurangnya penghormatan terhadap presedin, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Bila mengajukan pasal penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) pun tidak akan manjur karena para demonstran itu tidak melakukan perbuatan dimuka korban itu sendiri, sebagaimana disebut dalam KUHP. Lain halnya bila menggunakan Pasal 316 KUHP, pasal penghinaan terhadap orang yang ada dalam lembaga penguasa atau badan umum ketika dia sedang atau karena dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang sah. Demikian pula pada Pasal 207 KUHP tentang pasal penghinaan dengan lisan atau tulisan, tetapi bukan dengan perbuatan membawa kerbau. Obyek kejahatan berdasarkan Pasal 207 adalah penguasa dan badan umum. Yang dimaksud dengan penguasa adalah badan-badan public atau pemerintah yang memegang atau melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan umum. Sedangkan Badan Umum adalah semua badan bukan badan public, tetapi melaksanakan pekerjaa atau pelayanan untuk kepentingan umum.
Pasal yang lebih spesifik yang bisa menjerat para demonstran adalah perbuatan memaksa hewan untuk berada diluar habitatnya, apalagi bila menyiksa dan membunuh hewan seperti animal abuse atau animal cruelty yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pada ayat 1 huruf 1 dalam pasal tersebut berkenaan dengan perbuatan demonstran yang melampau batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, diancam penjara paling lama tiga bulan.
Sebagian masyarakat Indonesia cenderung memandang rendah derajat binatang sehingga cenderung mengabaikan faktor penyiksaan hewan, termasuk bila menyertakan dalam aksi demonstrasi. Padahal sebagai makhluk hidup, hewan-hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Bandingkan dengan masyarakat Cina yang menjadikan binatang sebagai symbol kelahiran yang dikenal dengan istilah shio, misalnya shio kerbau, shio babi, shio anjing dan seterusnya.
Didalam dunia binatang, kerbau memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Sifat positif binatang kerbau adalah stamina yang kuat, gampang diajak bekerjasama, dan pekerja keras. Sementara sifat negatifnya adalah lamban bergerak, badan besar, dan sudah pasti bodoh. Memang pada dunia binatang dikenal beberapa yang pintar seperti anjing yang dapat dijadikan partner bagi polisi dalam mengendus kejahatan.
Demo Alegoris
Demonstrasi dengan membawa simbol-simbol seperti binatang adalah demonstrasi alegoris. Demo alegoris biasanya berjalan dengan santun tanpa tindak kekerasan. Berbeda halnya dengan demonstrasi anarkis yang menggunakan aksi-aksi kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, seperti membakar benda-benda tertentu dengan maksud menarik perhatian. Namun anehnya, demo alegoris pada peringatan 100 hari SBY-Boediono banyak yang mencapkan tidak beretika dan tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran. Benarnya demikian?
Demonstrasi merupakan tautan antara aksi dan reaksi. Peringatan para demonstran dengan simbol “kerbau” karena selama ini melihat pemerintahan yang dipimpin SBY sangat lamban dalam menyelesaikan agenda nasional, baik yang mereka rumuskan dalam forum National Summit maupun penyelesaian skandal Bank Century. Maka sebagai bahasa komunikasi non-verbal, simbol “kerbau” itu sangat pas diidentikkan dengan fisik “SBY” yang berbadan besar dan lamban bergerak.
Bila SBY berpikiran positif, maka pesan non-verbal itulah yang ditanggapi dengan menunjukkan kinerja positif sebagaimana tuntutan rakyat yang diusung para demonstran itu. Bila menanggapinya dalam pidato, maka substansi aksi demo seyogyanya yang menjadi bahan evaluasi pemerintahannya, bukannya masalah kerbau yang berbau artifisial. Tuntutan demonstran substansinya adalah penyelesaian masalah century yang bertendensi korupsi, karena tema korupsi inilah yang menjadi tema umum kampanye SBY-Boedion pada saat pemilihan presiden tahun 2009 silam. Namun alih-alih menyelesaikan kasus century, justru SBY dan partai pendukungnya (utamanya Partai Demokrat) menyebarkan wacana reshuffle kabinet menyikapi menjelang penuntasan investasi kasus Century oleh Pansus Angket Century DPR.
Berbicara tentang etika dalam berdemonstrasi, sebenarnya demonstrasi dengan membawa kerbau jauh lebih santun ketimbang aksi-aksi Ruhut Sitompul (anggota Fraksi Demokrat) didalam sidang Pansus Hak Angket Century. Kata-kata “bangsat” yang sering keluar dari mulut politisi yang berlatarbelakang pengacara itu bisa jadi pangkal dari aksi para demontran. “Bangsat” sendiri adalah binatang kecil yang sering berkeliaran didalam tempat tidur yang tidak bersih.
Kata-kata bijak Aung San Suu Kyi - pejuang demokrasi Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 silam - mungkin bisa menemani renungan kita tentang politik Indonesia, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak watak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai,”
Binatang kerbau termasuk dalam sub-family Bovinae, dan genus Buballus. Kerbau yang ada di wilayah Indonesia dikenal ada dua jenis yakni: pertama, kerbau sungai (River Buffalo) yang mempunyai 48 kromosom (24 pasang kromosom), misalnya kerbau Murrah yang ada di Sumatera Utara; dan kedua, kerbau lumpur atau rawa (Swap Buffalo) yang mempunyai 50 kromosom (24 pasang kromosom). Jenis kedualah yang paling banyak populasinya karena jenis kerbau pekerja dan penghasil daging, sedang jenis pertama adalah penghasil susu perah populasinya sangat sedikit. Dari seluruh populasi kerbau di seluruh dunia, hanya 2 persen yang berada di Indonesia.
Meski populasinya hanya dua persen, berita tentang kerbau Indonesia telah menyebar luas ke seluruh dunia sehubungan dengan demonstrasi kerbau “Si Buya” di depan Istana Negara. Tulisan “Si Buya” tersebutlah yang menjadi pemicu Presiden SBY tersindir dan menjadi perbincangan para petinggi negara ketika melangsungkan hajatan kenegaraan bersama semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat pada Selasa (02/2/2010).
Reaksi Presiden SBY tersebut seakan menjadi pemantik dimulainya polemik tentang persoalan etika dalam berdemonstrasi. Bagi para pendukung SBY, demonstrasi dengan melibatkan kerbau sangat tidak etis. Apalagi binatang kerbau bagi masyarakat Indonesia diidentikkan sebagai symbol kebodohan dan kelambanan. Berbeda dengan astrologi orang China yang melambangkan kerbau sebagai simbol kehebatan. Pihak kepolisian pun kesulitan menangkap demonstran yang membawa binatang karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Bila menggunakan tuduhan pencemaran nama dengan adanya nama “Si Buya” sangat tidak beralasan, kecuali bila bertuliskan “Si Buyo” maka bisa saja dijadikan akronim “Susilo Bambang Yudhoyono”.
Sebenarnya masyarakat tidak banyak yang menaruh perhatian kehadiran kerbau dalam aksi demonstrasi pada 28 Januari. Namun SBY sendiri yang mempopulerkan kehadiran kerbau dalam demonstrasi dan mendapatkan liputan media massa secara luas. Sepertinya scenario mengangkat demonstrasi kerbau “Si Buya” untuk mencitrakan dirinya yang kembali teraniaya sehingga public kembali berpihak kepadanya. Namun bukannya citra positif yang didapat, justru public semakin mempertegas imaji tentang sosok pribadi SBY yang sebenarnya sebagai sosok melankolis yang doyan mengeluh.
Pendukung Presiden SBY pun tidak bisa secara langsung mengajukan pasal-pasal pidana kepada para demonstran itu. Penyebabnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir norma tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2006 dalam putusannya No. 022/PUU-IV/2006. Namun MK tidak menganulir penghinaan terhadap kepala negara asing atau wakil negara asing di Indonesia. Bagi para penghina kepala negara asing, ancaman pidananya sangat berat maksimun 5 tahun. Memang harus diakui bahwa dampak putusan tersebut menyebabkan berkurangnya penghormatan terhadap presedin, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Bila mengajukan pasal penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) pun tidak akan manjur karena para demonstran itu tidak melakukan perbuatan dimuka korban itu sendiri, sebagaimana disebut dalam KUHP. Lain halnya bila menggunakan Pasal 316 KUHP, pasal penghinaan terhadap orang yang ada dalam lembaga penguasa atau badan umum ketika dia sedang atau karena dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang sah. Demikian pula pada Pasal 207 KUHP tentang pasal penghinaan dengan lisan atau tulisan, tetapi bukan dengan perbuatan membawa kerbau. Obyek kejahatan berdasarkan Pasal 207 adalah penguasa dan badan umum. Yang dimaksud dengan penguasa adalah badan-badan public atau pemerintah yang memegang atau melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan umum. Sedangkan Badan Umum adalah semua badan bukan badan public, tetapi melaksanakan pekerjaa atau pelayanan untuk kepentingan umum.
Pasal yang lebih spesifik yang bisa menjerat para demonstran adalah perbuatan memaksa hewan untuk berada diluar habitatnya, apalagi bila menyiksa dan membunuh hewan seperti animal abuse atau animal cruelty yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pada ayat 1 huruf 1 dalam pasal tersebut berkenaan dengan perbuatan demonstran yang melampau batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, diancam penjara paling lama tiga bulan.
Sebagian masyarakat Indonesia cenderung memandang rendah derajat binatang sehingga cenderung mengabaikan faktor penyiksaan hewan, termasuk bila menyertakan dalam aksi demonstrasi. Padahal sebagai makhluk hidup, hewan-hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Bandingkan dengan masyarakat Cina yang menjadikan binatang sebagai symbol kelahiran yang dikenal dengan istilah shio, misalnya shio kerbau, shio babi, shio anjing dan seterusnya.
Didalam dunia binatang, kerbau memiliki sifat positif maupun sifat negatif. Sifat positif binatang kerbau adalah stamina yang kuat, gampang diajak bekerjasama, dan pekerja keras. Sementara sifat negatifnya adalah lamban bergerak, badan besar, dan sudah pasti bodoh. Memang pada dunia binatang dikenal beberapa yang pintar seperti anjing yang dapat dijadikan partner bagi polisi dalam mengendus kejahatan.
Demo Alegoris
Demonstrasi dengan membawa simbol-simbol seperti binatang adalah demonstrasi alegoris. Demo alegoris biasanya berjalan dengan santun tanpa tindak kekerasan. Berbeda halnya dengan demonstrasi anarkis yang menggunakan aksi-aksi kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, seperti membakar benda-benda tertentu dengan maksud menarik perhatian. Namun anehnya, demo alegoris pada peringatan 100 hari SBY-Boediono banyak yang mencapkan tidak beretika dan tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran. Benarnya demikian?
Demonstrasi merupakan tautan antara aksi dan reaksi. Peringatan para demonstran dengan simbol “kerbau” karena selama ini melihat pemerintahan yang dipimpin SBY sangat lamban dalam menyelesaikan agenda nasional, baik yang mereka rumuskan dalam forum National Summit maupun penyelesaian skandal Bank Century. Maka sebagai bahasa komunikasi non-verbal, simbol “kerbau” itu sangat pas diidentikkan dengan fisik “SBY” yang berbadan besar dan lamban bergerak.
Bila SBY berpikiran positif, maka pesan non-verbal itulah yang ditanggapi dengan menunjukkan kinerja positif sebagaimana tuntutan rakyat yang diusung para demonstran itu. Bila menanggapinya dalam pidato, maka substansi aksi demo seyogyanya yang menjadi bahan evaluasi pemerintahannya, bukannya masalah kerbau yang berbau artifisial. Tuntutan demonstran substansinya adalah penyelesaian masalah century yang bertendensi korupsi, karena tema korupsi inilah yang menjadi tema umum kampanye SBY-Boedion pada saat pemilihan presiden tahun 2009 silam. Namun alih-alih menyelesaikan kasus century, justru SBY dan partai pendukungnya (utamanya Partai Demokrat) menyebarkan wacana reshuffle kabinet menyikapi menjelang penuntasan investasi kasus Century oleh Pansus Angket Century DPR.
Berbicara tentang etika dalam berdemonstrasi, sebenarnya demonstrasi dengan membawa kerbau jauh lebih santun ketimbang aksi-aksi Ruhut Sitompul (anggota Fraksi Demokrat) didalam sidang Pansus Hak Angket Century. Kata-kata “bangsat” yang sering keluar dari mulut politisi yang berlatarbelakang pengacara itu bisa jadi pangkal dari aksi para demontran. “Bangsat” sendiri adalah binatang kecil yang sering berkeliaran didalam tempat tidur yang tidak bersih.
Kata-kata bijak Aung San Suu Kyi - pejuang demokrasi Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 silam - mungkin bisa menemani renungan kita tentang politik Indonesia, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak watak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai,”
Langganan:
Postingan (Atom)























 a href="http://v2.taketheglobe.com/index.php?ref=primus74" target="_blank" rel="nofollow">
a href="http://v2.taketheglobe.com/index.php?ref=primus74" target="_blank" rel="nofollow">